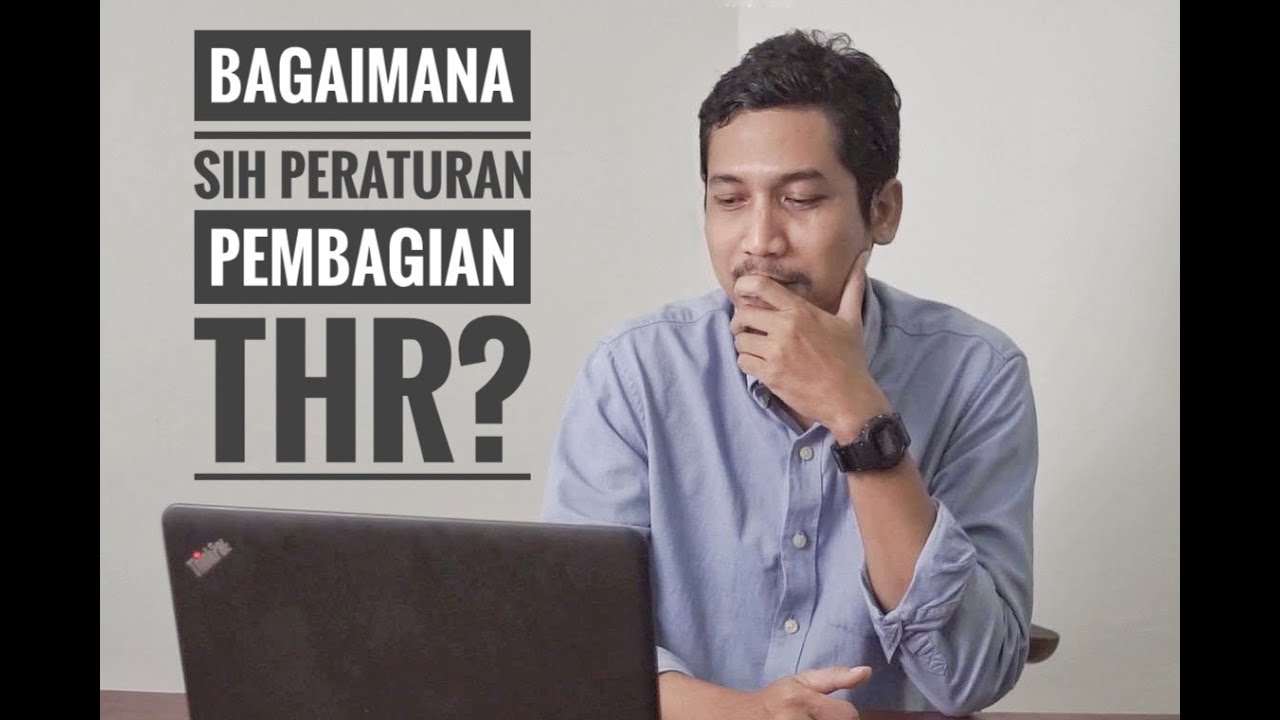Kritik atas tulisan Ulil Abshar Abdalla di Kompas.id berjudul Isu Tambang, antara Ideologi dan Fikih
Nahdlatul Ulama seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan negara dan memberikan kerangka etik dalam setiap agenda pembangunan. Bukan malah menjadi kepanjangan tangan proyek negara dan pemerintah yang sudah terbukti menciptakan berbagai kerusakan alam dan ketimpangan sosial.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2024, PBNU menjadi ormas keagamaan yang pertama kali menyetujui dan mengajukan diri untuk menjadi penerima lahan konsesi tambang batubara. Ketua PBNU, Gus Yahya, menyambutnya sebagai hal positif, apalagi NU merupakan organisasi besar yang punya pengurus sampai ke level ranting di perdesaan di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, kebijakan ini pun menuai pro-kontra. Pasalnya, kebijakan tentang pengelolaan tambang ini sudah lama dikritik oleh berbagai kalangan, termasuk dari kalangan NU sendiri. Dalam sejarah tambang (di) Indonesia, belum ada satu pun yang berhasil meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Semuanya nyaris berakhir dengan kerugian lingkungan dan sosial yang cukup besar. Lingkungan dikorbankan dan orang-orang di sekitar lokasi pertambangan terpaksa menerima konsekuensinya: mulai dari kesehatan yang memburuk, lingkungan yang rusak, hingga ancaman musnahnya sebuah kampung.
Klaim-klaim PBNU yang melibatkan kalangan ahli di bidang pertambangan tak membuat apa yang telah dilakukan menjadi hal yang baik. Sebab, pertambangan sebagai industri ekstraktif sudah lama dikritik oleh banyak kalangan karena daya rusaknya yang terlampau besar, baik dilihat dari segi lingkungan maupun sosial.
Selain itu, tawaran tambang tersebut akan membuat lembaga keagamaan hanya menjadi legitimasi kekuasaan dan akan terjadi perusakan lingkungan secara lebih masif. Dan kenyataan ini akan mengulang berbagai sejarah Sunni di masa lampau yang membuat ulama dan intelektual menjadi legitimasi kekuasaan politik seperti dari era Al-Ghazali di era Abad Pertengahan sampai era Nuruddin Ar-Raniry di masa Kerajaan Aceh.
Baca juga: Eksil, 1965, dan Arah Politik Permaafan Kita
Selain itu, apa yang dilakukan PBNU dengan menerima konsesi tambang dari pemerintah semakin memperkuat tesis Ahmet T. Kuru terkait perselingkuhan para intelektual dan kelompok keagamaan dengan negara. Para intelektual dan kelompok di bawah PBNU tidak lagi independen dan sangat bergantung dengan lahan basah dari negara.
Perselingkuhan agama dan negara menjadi titik tolak dari tesis kemunduran Islam Ahmet T. Kuru. Baginya, Islam mengalami degradasi intelektual dan kehilangan pengaruh karena ulama-intelektual menjadi bemper kekuasaan dan bekerja di bawah pengaruh kuat negara. Hal ini membuat ulama-intelektual tak lagi independen saat melakukan eksperimen atau mengeluarkan fatwa dan bahkan keputusan. Alhasill, segala hal yang dikeluarkan ulama-intelektual tersebut menjadi kepanjangan tangan dari penguasa.
Keputusan PBNU terkait tambang batubara juga direspons positif oleh Ulil Abshar Abdalla dalam opininya di Harian Kompas. Ulil menulis: Salah satu kaidah yang dipakai oleh para kiai ialah jika ada dua mafsadah (ancaman), harus diusahakan sebuah langkah yang mengandung mafsadah paling minimal. Sayangnya, ia tidak menjabarkan apa dua ancaman itu sehinnga ia melumrahkan PBNU mengambil tawaran tambang dari pemerintah. Ataukah memang sebenarnya tak ada sama sekali urgensi PBNU mengambil tawaran itu?
Dengan menggunakan kaidah fikih idza ta’aradlat al-mafsadatani ru’iya akhaffuhuma, Gus Ulil terjebak pada pembenaran dan menutup mata soal efek tambang di banyak lokasi dan krisis iklim yang kian dirasakan di banyak tempat. Suhu makin panas, dan musim semakin sulit diprediksi.
Menurut siaran pers Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada 6 Mei 2024, dalam satu dekade terakhir, fenomena suhu panas di atas 36 derajat celcius terjadi di beberapa lokasi di Asia Tenggara. Di Indonesia, suhu terpanas terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, yang mencapai 37,8 derajat celcius pada 23 April 2024.
Selain itu, World Meteorological Organization (WMO) menyatakan bahwa suhu mengalami kenaikan tertinggi dalam sejarah pada 2023 dengan rata-rata kenaikan global 1,5 derajat celcius. Penyebab utama kenaikan suhu karena semakin meningkatnya emisi global karena aktivitas manusia yang bergantung pada industri ekstraktif seperti batubara, minyak, dan gas alam (Kompas.id, 21/6/2024).
Berdasarkan hal tersebut, tambang batubara menjadi salah satu muasal semakin memanasnya suhu bumi dan emisi global. Dalam kasus tambang, tidak ada yang paling minimal dari dua mafsadah (kerusakan) seperti yang dimaksud Gus Ulil. Tambang punya daya rusak yang paling maksimal dan tak ada lagi perdebatan mana yang terbaik. Sebaik-baiknya pertambangan adalah tidak melakukan penambangan. Daya rusak tambang terhadap sosial, budaya, dan lingkungan begitu besar.
Baca juga: Tak Hanya El Nino, Beras Mahal karena Rapuhnya Adaptasi Iklim Pertanian Kita
Di Kalimantan Timur, tambang batubara sudah pernah memusnahkan sebuah kampung transmigran di daerah Tenggarong. Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sepanjang 2011-2024, ada 47 anak meninggal sia-sia di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi. Selain itu, tambang batubara membuat warga di sekitar area tambang kesulitan air bersih.
Dengan demikian, penggunaan kaidah fikih idza ta’aradlat al-mafsadatani ru’iya akhaffuhuma dalam kasus tambang menjadi batal. Tambang sudah menjadi mafsadah sejak niat! Karena itu, seruan untuk meninggalkan pertambangan ekstraktif bukan pepesan kosong semata.
Jika Gus Ulil menggunakan legitimasi fikih untuk membenarkan penerimaan PBNU atas konsesi tambang, maka tulisan ini juga menggunakan kaidah ushul fikih untuk menolaknya. Salah satu kaidah fikih mengatakan “Dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih.” Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Karena itu, dengan kaidah ushul fikih ini, PBNU dan juga para Nahdliyin di mana pun berada mesti menolak tambang, bukan karena ada atau tidaknya ahli pertambangan, melainkan karena daya rusak yang diciptakan dari industri pertambangan.
Agama seharusnya menjadi seruan moral untuk menjaga semesta alam sekaligus menjadi penyeimbang atas kebijakan negara. Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan seharusnya tidak menjadi bemper kekuasaan yang kian represif dan otoritarian. Jika pemberian lahan konsesi kepada PBNU yang dilegitimasi oleh para intelektualnya berhasil lolos, NU tak lagi punya legitimasi moral atas seruan untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi karena NU sendirilah yang menjadi pelaku perusakan alam melalui badan usahanya.
Kembali ke Komitmen Masyarakat Sipil
Jika PBNU diserukan untuk menolak konsesi tambang batubara, apa yang mesti dilakukan? Ini menjadi pertanyaan penting bagaimana NU mengelola organisasi dan kecakapannya untuk mengelola finansial. Dari pernyataan Gus Yahya yang tayang di media massa, NU perlu uang dan karena itu menerima tawaran konsesi ini. NU mendadak menjadi pragmatis di hadapan kekuasaan Joko Widodo.
Namun, apa yang dikeluhkan Gus Yahya terkait kebutuhan finansial NU sangat bisa dibantah. Sejak dulu, apa yang dilakukan NU selalu bergantung kepada partisipasi jamaah di setiap kegiatan yang dilakukan. Gerakan “Koin Muktamar” pernah menjadi program PBNU secara organisasi yang luar biasa. Gerakan ini membuat NU tak lagi sekadar milik PBNU, tetapi juga milik para Nahdliyin atau warga NU.
Melalui gerakan Koin Muktamar, secara langsung NU mencegah infiltrasi politik uang di saat Muktamar NU dilangsungkan. Dengan cara tersebut, NU bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung pada kebaikan atau berharap kucuran proyek negara.
Selain itu, penerimaan konsesi tambang oleh PBNU tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan NU sejak zaman awal berdirinya. Terlalu mahal dan bahkan tak ada harga yang sebanding. Tambang hanya akan membawa PBNU dan juga para jamaahnya masuk dalam kubangan kapitalisme rente yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Baca juga: ARSIP AA NAVIS: Kesusasteraan Dihukum Karena Pengarang Tidak Punja Kekuatan Formil
NU harus kembali sebagai gerakan masyarakat sipil yang memberikan pendidikan politik untuk para Nahdliyin dan juga seluruh rakyat. NU sudah seharusnya menjadi bagian dari proses penyadaran politik terkait hak-hak dasar warga negara. Hal ini lebih baik daripada berharap menerima konsesi tambang yang sebagian korbannya adalah jamaah NU sendiri.
NU zaman Gus Dur barangkali menjadi gambaran terbaik bagaimana NU menjadi sebuah gerakan masyarakat sipil yang membela kaum-kaum yang termarjinalkan oleh pembangunan Orde Baru. Selain itu, NU di bawah kepemimpinan Gus Dur tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan mengambil keuntungan pribadi.
Dan NU hari ini mesti belajar banyak kepada saudara tuanya, Muhammadiyah. “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Karena itu, jika Gus Ulil melihat penolakan tambang sekadar persoalan ideologi dan tidak punya implikasi terhadap fikih, maka saya kira itu adalah pendapat yang cukup keliru. Tambang juga persoalan ushul fikih dan karena itu kita harus menolaknya!
Sebagai seorang yang lahir dari keluarga NU dan juga pernah sekolah di pesantren NU, serta pernah bergiat di organisasi anak muda NU, saya sangat kecewa dengan PBNU dan Gus Ulil yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan yang terus-menerus merusak alam.
Sekian.
**) Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi menerbitkan ini sebagai wadah untuk diskusi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat.