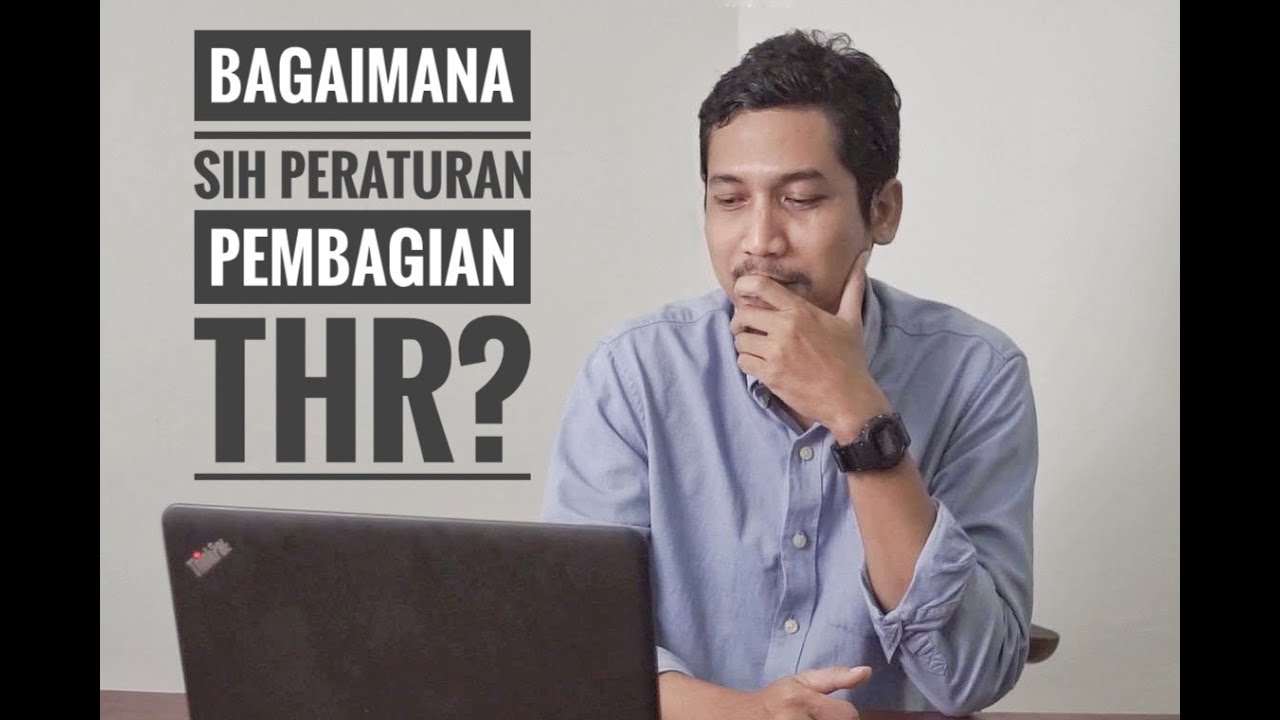Nelson Mandela dalam bukunya Long Walk to Freedom menulis: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”
Merenungi pernyataan itu, jika kita percaya pendidikan bisa mengubah dunia, ia benar belaka. Namun, pernyataan Nelson Mandela itu agaknya jauh panggang dari api, terutama saat kita melihat kondisi pendidikan dalam negeri. Ada prasyarat mendasar yang diperlukan agar pendidikan dalam negeri kita bisa optimal untuk menjadi sebuah “senjata untuk mengubah dunia”.
Tagar #janganjadidosen bisa menjadi pintu masuk untuk melihat kondisi pendidikan tinggi dalam negeri kita. Tagar ini sempat ramai di jagad media sosial dan menjadi perbincangan di berbagai artikel media massa, dilihat dari berbagai sisi. Tagar ini pada awalnya kebanyakan dibahas di media sosial oleh para dosen perguruan tinggi negeri atau PTN. Namun, mungkin banyak yang lupa bahwa tak sedikit pula dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta (PTS), yang dalam kesehariannya tidak dilindungi undang-undang dalam masalah pendapatan.
Untuk dosen PTN, sejumlah haknya tercantum dalam peraturan pemerintah atau undang-undang. Misal, di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dosen PTN yang menduduki jabatan fungsional mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Kita juga bisa minilik Peraturan Presiden Nomor 65/2007 tentang tunjangan dosen. Yang sedikit “menggelitik”, di dalamnya menyebutkan bahwa dosen yang menjabat sebagai guru besar akan mendapatkan tunjangan Rp 1,35 juta. Adapun dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai rektor dengan jabatan guru besar akan mendapatkan tunjangan Rp 5,5 juta. Itu di luar gaji pokok.
Lalu, bagaimana dengan dosen yang baru masuk, baru selesai kuliah magister, dan tidak memiliki pengalaman mengajar?
Baca juga: Beberapa PR Terkait Pelaksanaan Aturan ‘Publisher’s Rights’ di Indonesia
Menurut informasi yang saya baca, sebelum ada perhatian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan meningkatkan tunjangan dosen pada 2024, dosen PNS yang bekerja 0-1 tahun masuk golongan III dengan gaji pokok berkisar antara Rp 2,6 juta sampai Rp 4,7 juta per bulan. Sementara itu, untuk golongan paling tinggi, yakni golongan IV, kisaran gajinya Rp 3,04 juta sampai Rp 5,9 juta. Cukup waw (kecil), bukan?
Muncul pertanyaan, apakah pemerintah tahu seberapa sulit, butuh waktu berapa lama, dan butuh biaya berapa untuk menjadi guru besar? Saya rasa pemerintah tidak mengerti dan tidak tahu (atau tidak mau tahu?). Biasanya, jika ada kritik seperti ini, masyarakat umum atau beberapa oknum di pihak pemerintah akan membalasnya dengan “kenapa tidak ikut beasiswa?” atau “kenapa tidak ikut hibah riset?”
Apakah mereka mengetahui persaingan mendapatkan hibah dan beasiswa, baik untuk dosen PTN dan PTS, itu super-duper sulit? Tentu saja tidak sekadar mendaftar dan langsung berhasil lolos. Saingan di dalamnya bukan masyarakat biasa, tetapi mereka yang juga memiliki kemampuan setara atau bahkan lebih dari dosen itu sendiri. Belum lagi jumlah hibah dan beasiswa yang tak sebanding dengan jumlah dosen yang ada.
Sekarang saya coba bahas dosen non-ASN alias dosen PTS. Jika melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dosen PTS berhak mendapat gaji pokok dan tunjangan, tetapi nominalnya berdasar kemampuan universitas atau yayasan. Artinya, jika yayasan tersebut besar dan punya kekuatan finansial, otomatis pendapatan yang diterima dosen PTS pun besar. Namun, bagaimana jika tidak? Kondisi di lapangan yang saya tahu, yayasan (dengan kondisi keuangan terbatas) sekadar memberi gaji atau tunjangan dengan nominal di bawah bayaran pekerja pada umumnya.
Seorang kawan pernah protes masalah ini ke otoritas pemerintahan terkait. Namun, mereka tidak dapat membantu karena kewenangan pemberian upah dosen PTS ada pada yayasan yang menaungi universitas tempatnya mengajar. Pemerintah tidak ikut campur.
“Anda seharusnya bersyukur bisa jadi dosen, yang lain tuh susah cari kerja!” adalah kalimat yang paling sering kami dapatkan di media sosial setiap kami protes masalah pendapatan. Tentu saja kami bersyukur dapat pekerjaan yang terbilang bagus. Namun, ada hak yang layak kami terima atas kewajiban dari “pekerjaan bagus” yang sudah kami jalani itu. Lagi pula, bersyukur dan hak adalah dua hal berbeda, bukan?
Menjalani profesi sebagai dosen adalah sebuah tantangan di Indonesia. Setiap semester dosen dibebani dengan mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Semuanya mesti ada proposal yang diajukan, bukti, dan laporan yang cukup detail. Memang pemerintah memberikan dana tunjangan sertifikasi untuk para dosen dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sayangnya tidak semua dosen mendapatkan sertifikasi dosen. Ada yang masih dalam proses. Ada pula yang terlewat untuk menjalankan satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi dalam satu semester, sehingga ia harus menunggu dua tahun. Ada pula yang tidak punya dana untuk beragam tes persyaratan, seperti tes bahasa Inggris, potensi akademik, dan pekerti. Dana yang dibutuhkan untuk tes persyaratan itu nominalnya lumayan besar bagi kami.
Baca juga: Tak Hanya El Nino, Beras Mahal karena Rapuhnya Adaptasi Iklim Pertanian Kita
Haruskah saya iri dengan seorang teman yang menjadi dosen di sebuah universitas swasta di negara tetangga? Baru lulus program doktor, ia masuk universitas swasta dengan gaji setara Rp 20 juta per bulan.
Saya lihat, membiarkan dosen PTN atau PTS diupah kecil hanya membuat pendidikan tinggi kita bertarung dalam masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu urusan kesejahteraan para dosennya; Bukan masalah perbaikan riset guna meningkatkan persaingan global, bukan pula menciptakan lulusan yang berkualitas dan berguna di masyarakat, dan seterusnya.
Dengan kondisi kesejahteraan yang belum selesai, banyak dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Dampaknya, dosen tak maksimal menjalankan tugas utamanya, yakni melayani mahasiswa dan meneliti. Pada beberapa kasus, rendahnya pendapatan dosen ini membuat dosen rentan terjerat dalam praktik manipulatif-koruptif. Misalnya, jual-beli paksa buku perkuliahan hingga membuka jasa pembuatan skripsi (!). Hal lain bisa ditanyakan kepada mahasiswa: Saat bimbingan atau saat kelas berlangsung, apakah mereka pernah menjumpai dosen izin tidak hadir karena sibuk di tempat lain? Saya yakin banyak yang menjawab pernah.
Oleh karena itu, jika pemerintah ingin universitas di negeri ini menjadi world class university, menciptakan world class researcher, apalagi ingin menjadi universitas berbasis riset untuk PTN atau PTS dalam negeri, masalah kesejahteraan ini sangat perlu diperhatikan. Afterall, ini semua tentang political will saja.
**) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi menerbitkan ini sebagai wadah untuk diskusi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat.