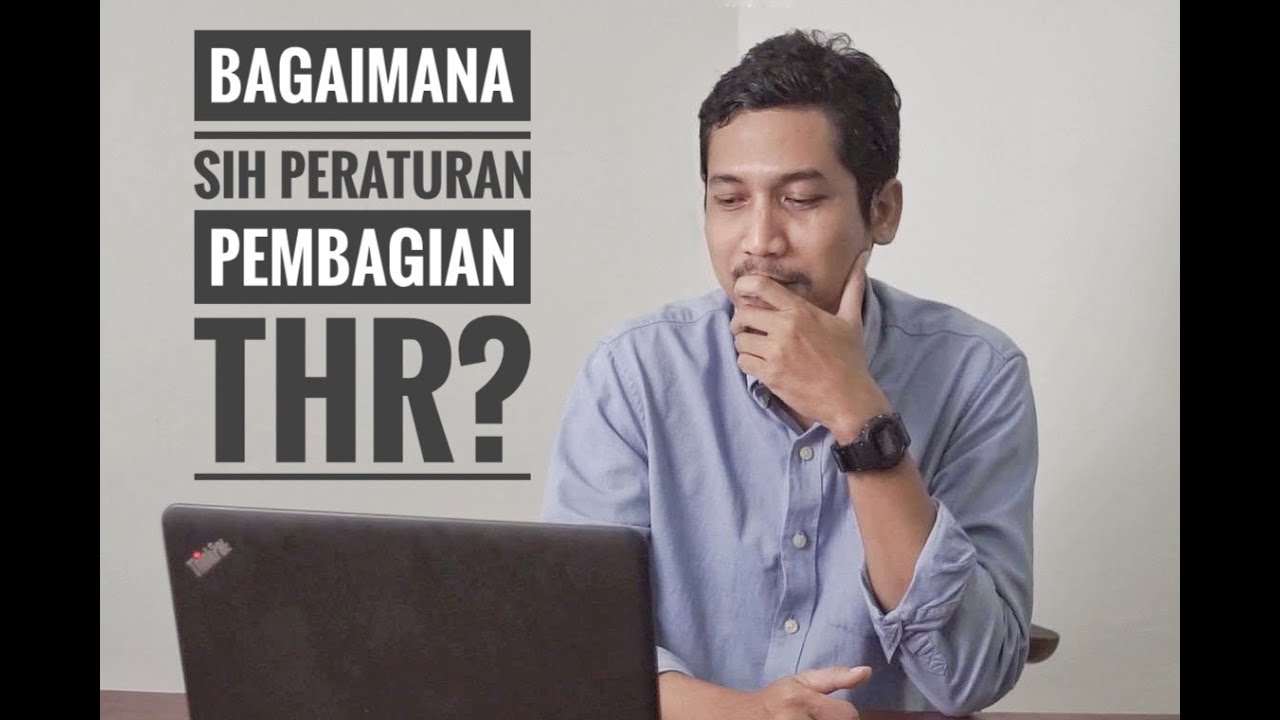Undu, lengkapnya Andi Mappatunru. Pria yang mungkin sekitar tiga puluhan tahun itu adalah dosen ilmu politik dan pemerintahan di salah satu perguruan tinggi negeri di Sulawesi Barat. Ia juga membuka usaha kecil-kecilan warung kopi yang diberi nama Centralismo. Letaknya di seberang bangunan Pusat Oleh-Oleh Mandar, Jalan Poros Majene-Polewali.
Centralismo adalah nama album band Sore. “Kurang saya minati sekarang Sore karena sudah tidak ada Mondo-nya (Mondo Gascaro, eks keyboardis/vokalis),” katanya.
Jika tak salah ingat, saya mengenal Undu pasca saya lulus SMK saat hijrah ke Yogyakarta. Saya bertemu dengannya di Asrama Majene Wisma Ammanna Pattolawali. Jika saya tak salah, ia diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, sedangkan saya, kurang lebih tiga minggu di Jogja, terpaksa kembali ke Balikpapan dan tidak jadi berkuliah di sana. Sebab, saya diterima di jurusan yang tak sesuai dengan keinginan.
Tak banyak saya mengenalnya. Yang saya tahu, ia suka basket dan bermain gitar. Setelah itu, kadang-kadang kami saling berkomentar di status Facebook. Itu pun jarang. Akhirnya, Sabtu, 20 Januari 2024, saya berjumpa lagi dengannya saat berkunjung ke Majene, kala kakak saya mengajak ngopi di Warkop Centralismo.

Di sudut belakang dan kanan warung kopinya ada rak buku. Yang di belakang, buku-buku dijual dan masih bersegel. Nah, buku yang dipajang di rak sebelah kanan adalah koleksi pribadinya, bisa dibaca di tempat. Yang membuat mata saya heran sekaligus terkesima adalah banyak buku-buku kiri yang jumlahnya puluhan dan tebal-tebal; ada terjemahan Indonesia, ada pula yang berbahasa Inggris.
Saya bertanya, apakah tak pernah ada aparat yang mengawasinya karena tumpukan buku yang ia pajang itu, yang ia pamerkan, dan ia persilakan pengunjung warung kopi membaca buku-buku itu? Dan saya yakin, seorang pembaca tipe Undu pasti senang bicara mengenai pemikiran kiri, sistem sosialis, perjuangan kelas, kapitalisme, revolusi, sistem pemerintahan, dan hal sejenisnya. Diskusi macam itu pasti tak terhindarkan di kedai kopinya.
Terus terang, katanya, ia pernah didatangi aparat karena mempersilakan siapa pun pengunjung membaca buku-bukunya. Apalagi, buku adalah ladang pemikiran yang, dalam kadar tertentu, bisa mempengaruhi atau “mengganggu” isi kepala pembaca. Dalam banyak hal, memang tak selalu begitu; ada kalanya pembaca buku mengkritik isi suatu buku dengan menulis buku pula. Itulah dialektika intelektual.
Saya pernah mendengar seseorang mengatakan, seperti membaca karya sastra, semua buku yang sudah kita baca, tanggapannya dikembalikan lagi ke pembaca. Sebab, esensi buku adalah buku. Dari buku, kembali lagi ke buku dan si pembaca. Jika orang sudah khatam Das Kapital-nya Karl Marx, apakah orang itu bisa dikatakan Marxis? Bisa jadi justru kebalikannya, yakni anti-Marxis.
Aku menulis, maka aku membaca
Jadi, dengan santainya Undu mengatakan, dirinya membaca semata-mata karena ingin menulis. Aku menulis, maka aku membaca; aku membaca, maka aku menulis. Apalagi, saat ini ia seorang dosen. Semua buku, jika bisa, ia ingin lahap—kalau ada waktu. Dan, tambah saya, agar tak keliru dan bisa jadi bahan pertanggungjawaban saat menulis.
Kadang, kutipan dari sebuah buku dibutuhkan untuk memperkuat argumen si penulis agar terlihat keren bahwa “saya tak sembarang nulis. Nih, ada metodologi atau teorinya (yang diacu)”.
Namun, kenapa buku-buku kiri yang lebih dominan di rak koleksinya? Bahkan bukunya tebal-tebal; ada yang cetakan pertama dari tahun 1950-an dan berbahasa Inggris. Ia cerita, berkat relasinya, ada buku yang didatangkan dari Benua Eropa.
Ia mengambil dan menaruh buku-buku itu di atas meja di hadapan saya. Ia tumpuk meninggi. Ia buka halaman depan salah satu buku, menjelaskan di mana ia membelinya, berapa harganya, dan kapan membelinya. Saya kurang menguasai bahasa Inggris, saya tak sanggup membacanya.
Sebenarnya, saat ini pun banyak buku-buku kiri yang diterjemahkan dan bertebaran di toko buku. Kadang, hasil terjemahannya banyak yang melenceng alias kaku, tak mudah dipahami; atau mungkin penerjemah yang salah mengartikan atau pembacanya yang kurang tekun?
Untuk itu, Undu bilang, jika ingin memahami isi sebuah buku yang lebih otentik, lebih baik membaca teks dari naskah asli. Atau, bisa juga membaca terjemahan dalam bahasa Inggris dari penerbit terkemuka, Penguin Books misalnya. Kalau versi bahasa Indonesia-nya, bisa dilihat penerjemahnya atau penerbitnya. Ia merekomendasikan beberapa rilisan buku terjemahan penerbit Yayasan Obor.
Beberapa buku milik Undu memang belum banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada yang berminat menerjemahkannya, tapi mungkin persoalannya dana. Perlu banyak waktu untuk membaca, meriset, dan memahaminya. Apalagi kalau penerjemahnya asing dengan topik di dalam buku.
Tak mungkin pula negara mau membiayai penerjemahan buku-buku kiri. Apalagi mau menerjemahkan ensiklopedia pemikiran kiri. Mungkin ceritanya akan berbeda jika ada bantuan atau suntikan dana hibah internasional. Itu pun pasti bertabrakan dengan izin percetakan. Sebab, istilah kiri sendiri masih dianggap tabu oleh sejumlah kalangan di negeri ini.
Beberapa penerbit independen—dikelola dengan selektif, beberapa secara kolektif, dengan modal tak terlalu besar—eksis di Indonesia. Yang serius dengan isu kiri, salah satu yang saya tahu, adalah Penerbit Marjin Kiri. Mereka menerjemahkan sejumlah teks berbahasa Inggris, Spanyol, atau Belanda. Kualitas terjemahan dan pengelolaannya amat baik karena diterjemahkan dari bahasa asli dan oleh orang yang menguasai isu di buku tersebut.
“Sebenarnya, saya banyak diskusi dan tukar cerita sama teman-teman. Ada dua orang tipe kenapa mengoleksi buku. Ada orang yang memang bukunya itu hanya ingin dia beli, tapi tak dibaca dan hanya jadi pajangan di rak buku (baca : mungkin kesannya pamer),” katanya.
“Ada juga, antropolog yang saya kenal, dia baca Das Kapital dari pertama sampai akhir. Itu tebalnya bukan main, dan kalau dibaca, perlu berapa tahun untuk membacanya,” lanjut Undu.
“Banyak yang salah mengartikan pemikiran Marx: langsung disangkutpautkan dengan agama. Umumnya, orang berprasangka, jika terlalu Marxis, kamu akan jadi atheis. Padahal, yang ngomong seperti itu belum pernah baca bukunya. Singkatnya, tak suka dengan buku itu, tak usah dibaca dan jangan berprasangka. Selesai! Saya baca buku-buku ini karena persoalan sekarang masih ada sangkut pautnya dengan teori yang dikemukakan Marx,” ceritanya.
Jika saja obrolan dan aktivitasnya membaca buku-buku itu secara terbuka ia lakukan di era Orde Baru, mungkin Undu sudah “diamankan”. Apalagi ia seorang dosen, bisa berlapis hukumannya, haha…
Katanya, dan itu Undu ulang-ulang, ide-ide Karl Marx jauh melampaui zaman. Dan itu terbukti bahwa hari ini permasalahan yang dihadapi umat manusia di seluruh dunia adalah tak terdistribusinya kekayaan dengan baik. Tak ada seorang pemikir, filsuf, ekonom, pemikir politik, atau sosiolog yang membicarakan hal itu jauh melampaui Marx.
Baca juga: Mengenang Ignas Kleden, Polemik Sastra 1997
Marx membedah kapitalisme dan meletakkan dasar pemikiran yang terus dikembangkan oleh banyak pemikir dunia hingga saat ini. Ia suudzon kepada Adam Smith yang berteori bahwa orang kaya adalah orang yang di masa silam rajin bekerja dan berhemat, sementara orang miskin adalah mereka yang malas bekerja dan boros.
Sepintas, uraian Adam Smith itu terkesan masuk akal. Namun, Marx punya prasangka lain dan meniliknya dari sisi sejarah. Dari sana, Marx menulis ada dua kemungkinan eksisnya si kaya dan si miskin. Pertama, kolonialisme. Para merkantilis Eropa, seperti kita semua tahu, di masa silam menjelajah dunia untuk menjajah, termasuk ke Nusantara, untuk mencari kekayaan. Di Nusantara mereka mencari rempah-rempah, juga budak, untuk dijual, dan akhirnya memperoleh kekayaan dari kerja-kerja itu.
Kedua, si kaya muncul dari pengkaplingan tanah. Di Inggris, misalnya, para raja punya kuasa atas tanah di wilayah kekuasaannya. Oleh raja, tanah-tanah itu kemudian dikapling dan diberikan semacam hak kelola kepada petinggi militer dan bangsawan kerajaan. Para bangsawan dan petinggi itu kemudian mempekerjakan orang-orang yang tak punya kedudukan istimewa alias rakyat biasa. Tanah itu boleh dikelola, tetapi para pengelola tanah mesti membagi hasilnya sebagian (atau lebih) kepada raja: bangsawan mengambil hasil sisanya dan sedikit membagi ke rakyat biasa yang bekerja di sana.
Dalam perkembangannya, tanah yang sebelumnya tak boleh dikapling kemudian dikapling oleh para bangsawan itu (Marx menyebutnya borjuis kota). Mereka membuat perkebunan dan peternakan dengan membuat sertifikat tanah sehingga tak sembarang orang bisa mengelola tanah itu.
Hal itu yang kemudian berkembang dan semakin kompleks hingga saat ini sehingga memunculkan si kaya dan si miskin dengan tingkat kesenjangan tinggi. Bahkan, kekayaan dikuasai segelintir orang—ada yang menyebut satu persen orang menguasai dua per tiga kekayaan dunia.
Marx membedahnya, bagaimana kapitalisme menjadi sebuah relasi sosial yang rapuh—di satu sisi ada orang menguasai tanah dan alat produksi menjadi kaya raya, di sisi lain orang yang bekerja menjadi buruh hanya memperoleh sedikit bagian dari kerjanya dan tak kunjung kaya. Keturunan si kaya sangat mungkin tetap kaya, keturunan si miskin akan melahirkan si miskin baru. Memang ada beberapa pengecualian orang miskin jadi kaya, tapi itu amat sedikit dan pasti dengan kondisi tertentu yang mendukung.
Penjelasan Marx masuk akal dan runut. Jika mengacu Adam Smith, andaikan saya seorang penyapu jalan, akankah saya kaya raya jika saya bekerja keras dan rajin menyapu seluruh jalan yang ada di sebuah kota dan menabung dengan gaji yang sedikit itu? Tentu tidak, bukan? Artinya, ada persoalan lain yang membuat adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Marx sudah membahasnya berlembar-lembar dengan detail, masuk akal, dan masih relevan sampai saat ini. Saya yang bekerja sebagai karyawan swasta sadar diri. Saya ada di posisi sebagai buruh yang ide, tenaga, dan pikirannya sudah diambil, dipakai, dikuras, dan diabdikan ke perusahaan. Sudah teken kontrak dengan janji atau pasal-pasal yang telah ditentukan. Datang dari jam segini, pulang jam segitu. Kerjakan pekerjaan ini dan dituntut harus bisa menguasai ini-itu. Harus disiplin, patuh, dan produktif; bagaimana mematenkan barang mentah menjadi barang jadi. Sekeras apa pun saya bekerja, sampai sakit-sakit pun, saya tak mungkin sekaya pemilik perusahaan; sekalipun ditambah rajin menabung.
Kaum papa dan nyaleg

“Kenapa dulu banyak yang menyebar dogma dan memfitnah Marx itu anti Tuhan atau ateis?” lanjutnya. Memang, jika mendalami ide-idenya tanpa membaca utuh pemikiran Marx, ada saja yang jatuh pada kesimpulan itu.
Kemungkinan hal itu muncul dari kutipan yang tersebar sepotong-sepotong dari tulisan Marx, yakni “Agama…. adalah candu/opium”. Saya pribadi belum membaca naskah asli teks tersebut. Untuk melacak maksud detailnya, kita perlu membaca detail tulisan utuh tersebut. Ini bisa menjadi diskusi yang sehat dengan membaca teks aslinya secara utuh. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk membahas ini secara detail dengan membaca naskah aslinya dan menelaah analisis atas tulisan tersebut.
“Sekarang ini pun kadang perusahaan mendatangkan seorang agamawan. Mereka menyampaikan ceramah singkat dan mengutip kalimat kiasan yang setiap katanya diselipi kata ‘sabar, sabar, sabar, dan sabar’. ‘Kerja keras, kerja keras, dan kerja keras’. Tak ada yang salah dengan kalimat itu, kan?” timpal kakak saya. Ia memang sibuk dengan tugas-tugasnya di komputer jinjing. Namun ia juga kadang ikut nimbrung bicara. Kami semua tertawa. Paling tidak, menertawakan diri sendiri itu sangat menyenangkan.
Gaji murah, tak banyak menuntut, bisa disuruh macam-macam dan mau melakukan apa saja, dan yang didapatkannya pun poinnya hanya satu. Sekali lagi, hanya satu! Itulah persoalan yang dihadapi pekerja dewasa ini (sangat mungkin terjadi sejak dulu).
Baca juga: Yang Mengerikan dari “Ikam Hanyarkah di Samarinda?”
Saya menimpali, bahasa kiasan yang kadang dipakai oleh orang yang punya semangat juang tinggi dan terkesan sok bijaksana (padahal menderita), atau, pemodal yang sudah terlalu banyak makan keringatnya orang. Tak tahu kalimat itu hasil kutipan dari mana dan ide pemikirannya dari mana. Kalimat ini bertebaran di mana-mana. Kadang dipakai sebagai insta story, WA story, atau sebuah caption yang gambarnya si doski seolah-olah lagi kerja keras atau gambar yang mereka comot dari mana atau apa pun namanya. Kalimatnya begini:
“Peliharalah tempat di mana kamu bekerja. Jaga nama baiknya. Sekalipun tidak membuatmu kaya, tapi bisa membuatmu hidup.”
Kita semua lagi-lagi tertawa. Dan, menertawakan diri sendiri.
Harus bisa melawan. Minimal, melawan diri sendiri. Jangan beranggapan bahwa kemiskinan itu sudah berakar, sudah ditakdirkan, jalannya sudah seperti ini; dan berpikir tak usah lagi diotak-atik atau coba-coba berusaha.
Hapus semua pemikiran seperti itu
Mungkin ada yang bilang, “Berharap saja sama jaminan sosial, bantuan langsung tunai, atau bantuan-bantuan sosial lainnya yang dibiayai negara. Bukannya kaum papa dipelihara negara dan sudah ditakdirkan seperti ini dan tak usah seperti itu?”
Nah, sejumlah pemikir kiri tak hanya berhenti pada hal tersebut. Kata kuncinya adalah kesadaran. Sadar bahwa kemiskinan adalah persoalan struktural; sadar bahwa ada persoalan mendasar yang menyebabkan kemiskinan; sadar bahwa kemiskinan adalah akibat sistem yang tak adil; dan sadar itu bisa dilawan dengan mengetahui bagaimana sistem tak adil itu bekerja.
“Orang miskin itu tidak ditakdirkan! Ah, entah dari mana itu berasal. Jangan ada ide-ide semacam itu,” kata Undu.
Kemudian, Undu lagi-lagi menjelaskan bagaimana wujud perlawanan itu: perjuangan kelas, kolektivitas, dan seterusnya dan seterusnya. Saya hanya mendengarkan, sedikit-sedikit agak paham apa yang dikatakannya, dan dalam hati saya bergumam.
“Mengutip salah satu sastrawan yang saya kagumi, Widji Thukul: Hanya ada satu kata: lawan!”
Sebelum menutup omong-omong masalah kapitalisme dan kaum papa, saya cerita sedikit mengenai persoalan pekerja yang ada di kota tempat tinggal saya, Balikpapan. Apa saja yang dihadapi dan apa saja persoalannya. Ia mendengarkan. Dari itu, ia menarik kesimpulan bahwa untuk mengubahnya saat ini, saya mesti nyaleg.
Lho?
“Makanya nyaleg. Biar ubah sistem itu. Nanti di tahun yang akan datang kamu nyaleg saja, Fian. Bukan main, gaji DPR di kabupaten sini saja Rp 20 juta. Belum lagi dana-dana lainnya. Itu belum bersih. Lima tahun kamu lakukan itu di kabupaten ini, gaji segitu sudah besar sekali,” katanya, sambil tertawa.
Kemudian, yang di sebelah menimpal, “Betul itu. Enak betul. Pokoknya nyaleg. Orang enak itu. Ongkang-ongkang. Tinggal datang, isi absen, duduk. “Sepakat? Ya, sepakat.” Pulang dan jalan-jalan. Tinggal begitu saja. Enak, kan?”
Kami semua ketawa.
Ahmad Dhani si makrifat cinta
Kami melanjutkan obrolan ke musik. Dari segi penulisan lagu, Ahmad Dhani tetap berada satu tingkat di atas sejumlah musisi lain. Itu menurut versi saya. Saya mengatakan, sebelum mendengarkan Ahmad Dhani di Dewa 19 dengan format vokalis Once Mekel, alangkah baiknya mendengarkan saat Ari Lasso jadi vokalis di album “Pandawa Lima”. Bagaimana keganjilan gebukan drum Wong Aksan yang kawin dengan alunan bass mendiang Erwin Prasetya. Atau, penulisan lirik Ahmad Dhani sebelum mencintai “Makrifat Cinta”. Cinta yang benar-benar cinta.
Saya menyebut “Makrifat Cinta” karena setelah Once bergabung mengisi vokal dan setelah album “Bintang Lima”, beberapa album Dewa diselipi kata ‘cinta’: “Cintailah Cinta” (2002), “Laskar Cinta” (2004), dan “Kerajaan Cinta” (2007). Dan di setiap album, juga diselingi dengan lagu dan kata-kata cinta. Cinta, bagi si Dhani, dalam arti yang tak gombal dan menye-menye. Eksklusif. Bisa jadi, cintanya itu adalah cinta yang benar-benar cinta. Artinya, ditujukan pada Yang Maha Mencintai.
Agak urakan, ganjil, cadas, penuh improvisasi, tapi berbobot. Agak nge-jazz, soft, dan dibalut alternatif rock. Terbukti di lagu protes keras terhadap politik “Aspirasi Putih” dengan riff gitar Andra Ramadhan yang garang, melengking, dan melodius. Lagu “Cindi”, “Aku di Sini Untukmu”, “Sebelum Kau Terlelap”, “Suara Alam”, “Kirana”, “Petuah Bijak”… Waduh, pokoknya dengarkan sendiri satu album.
Dari album itu, kamu akan berpikir bahwa musik Dewa-nya Ahmad Dhani itu—disandingkan dengan Marx yang kiprahnya melampaui zaman—soal musik, Ahmad Dhani jauh melampaui zaman. Titik! Wajar jika Ahmad Dhani suka ngeritik masalah lagu dan merasa berada di atas. Sebab, musik-liriknya itu, lagi-lagi saya katakan, jauh melampaui zaman.
“Apalagi di lagu ‘Sudah’. Kok, bisa ya, Ahmad Dhani ciptakan lagu patah hati tapi kesannya cool, elegan, dan kesannya tidak patah hati. Dan di lagu itu, memang Ahmad Dhani yang harus nyanyikan,” ujar Undu.
Kakak saya memotong, “Kalau ‘Sudah’ itu dari Ahmad Band. Pasca Dewa vakum. Albumnya Ideologi Sikap Otak di tahun ‘98. Foto albumnya Ahmad Dhani pakai songkok kayak Soekarno. Dewa tak ada vokalis. Bagaimana tidak keren Ahmad Band, di situ ada bass Bong Q (eks Slank), gitaris Pay Burman (eks Slank), Andra, dan Wong Aksan…”
“Mana ada Wong Aksan jadi drummer. Dia juga keluar di Dewa dan yang isi drumnya itu Bimo eks drummer Netral,” potong saya.
“Mana yang lebih enak didengar, dari segi suara, Ari Lasso apa Once?” kata saya, bertanya ke Undu.
“Emm, Once.”
“Jika saya memilih, saya memilih Ari Lasso. Entah dari segi suara, gaya bermusik, soul dan karakternya. Itu menurut saya, ya kan. Hehehe.”
Untuk penyanyi sekarang, Undu menyebut nama Romantic Echoes. Beberapa vokalis tenar jika ditanya mengenai siapa musisi sekarang yang konsisten dan berkenan di hati, yang ia lihat wawancaranya di youtube dan ia dengarkan lagu-lagunya, katanya, mayoritas menyebut Romantic Echoes. Ia menyarankan saya mendengarkannya.
Saya menambahkan. Untuk konsep, musikalitas, visi bermusik, dan konsistensi penciptaan lagu, saya memilih solois Pamungkas. Itu menurut saya. Kami bercerita mengenai band-band indie. Efek Rumah Kaca, David (eks) “Naif”, White Shoes and The Couples Company, Danilla, Pamungkas, The Sigit, The Adams, Payung Teduh, dan sebagainya. Saya menyebut dua band Makassar: Kapal Udara dan Theory of Discoustic. Nama terakhir Undu tak pernah dengar.
Melihat band Sore saat ini banyak yang ditinggal personilnya, Undu lagi-lagi mengatakan, Sore itu sudah hilang jiwanya. Jiwanya itu ada di Mondo Gascaro. Kata saya, jika Ade Paloh adalah malam, maka Mondo adalah siang. Saya bertanya apakah pernah melihat secara langsung penampilan Sore? Mondo solo? Ia menjawab tak pernah. Saya sudah menontonnya langsung ketika konser di Balikpapan.
“Wah, mestinya harus itu. Tapi memang benar, Sore tampil itu memang menurut saya ada yang kurang. Ade Paloh terasa main-main. Berbeda dengan Mondo. Mondo untuk konsep tampil live, musikalitasnya oke sekali,” kata saya.
Ia katakan, untuk lirik, aneh sekali Sore bisa menciptakan lirik yang diulang-ulang seperti “mati suri di taman”. Kok bisa sampai sejauh itu. “Mati suri di taman” liriknya, judulnya “Setengah Lima”. Saya katakan, untuk komposisi musik (walau liriknya bahasa Inggris), “Karolina” jadi andalan di telinga.
Karolina, katanya, arti dari lagu itu pasti ada sangkut-pautnya dengan bercinta alias ng*w*.
“Tapi. . . o, o, o, tidak dengan istri alias belum nikah dengan istri. Bisa saja pas masih bujangan, pas masih nakal-nakalnya, atau sedang di luar saat jalan-jalan, ketemu, dan bagaimana-bagaimana itu urusannya masing-masing. Hahahaha”. Kami semua tertawa. []
Januari, 2024
*) Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi menerbitkan ini untuk membuka ruang diskusi dan bertukar pikiran.
Catatan: Tulisan ini sudah mengalami sejumlah pengeditan pada bagian “agama….adalah candu/opium” untuk menghindari misinformasi pada Rabu (14/2/2024) pukul 13.00 Wita.