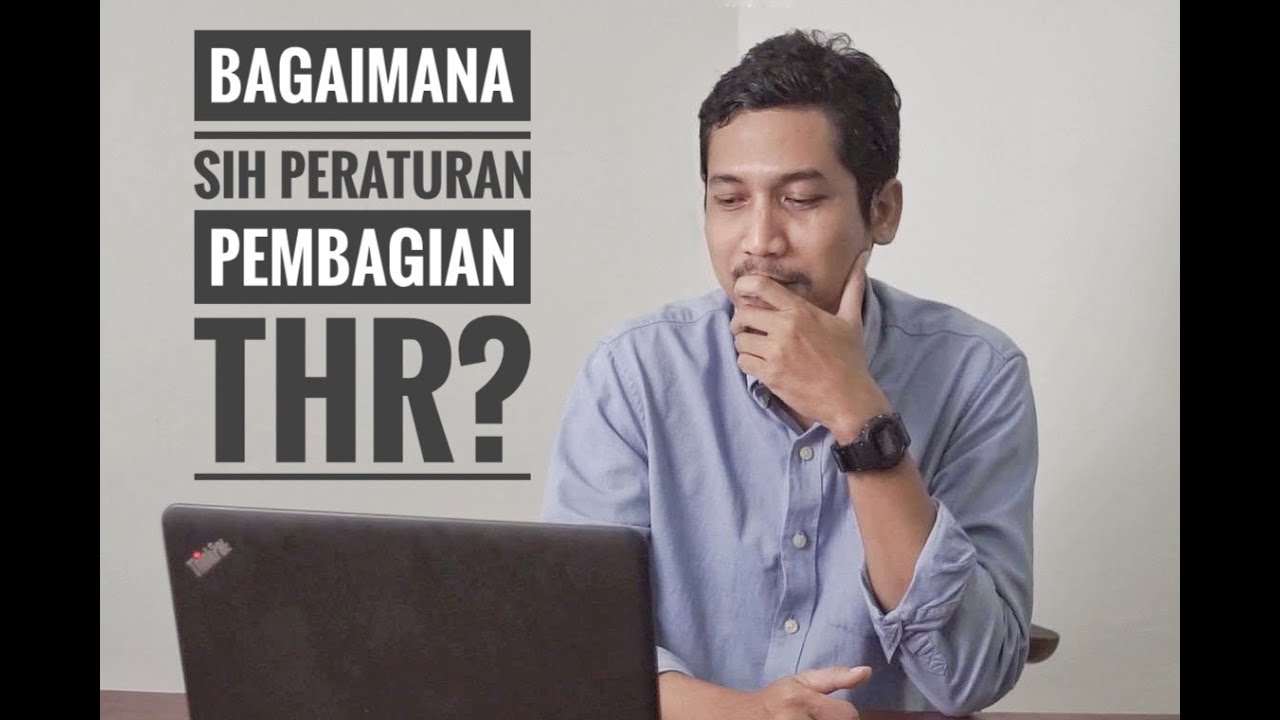Oleh:
Ubaidillah dan Jalu Lintang Yogiswara Anuraga
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya
***
LAKON pewayangan Petruk Dadi Ratu dalam kacamata demokrasi dianggap sebuah pencapaian. Ia bermakna kursi kepemimpinan tidak hanya dapat diduduki salah satu kelompok saja, tetapi semua potensial. Garis kepemimpinan tidak lagi mengikuti garis darah atau kekerabatan. Namun demikian, lakon ini dapat pula dianggap sebagai mal-manajemen karena orang yang salah berada di posisi yang salah sebagaimana kondisi berkebalikan dari kredo the right man on the right place. Demokrasi tidak lagi mengenal pembagian berbagai macam status di masyarakat.
Demokrasi bahkan mencibir klasifikasi pandita, satria, dan sudra sebagai pengkastaan status sosial masyarakat yang beku dan kaku tanpa ada kesempatan melakukan mobilitas sosial vertikal. Tulisan ini mengajukan klasifikasi pandita-satria-sudra sebagai pembagian orientasi batin, bukan sebagai stratifikasi sosial untuk memahami Petruk dadi ratu dalam konstelasi demokrasi. Pandita berkutat dengan pekerjaan berkenaan dengan ilmu, kebenaran, sampai nilai-nilai transendental untuk merohanikan yang material. Mereka memberikan makna batin dari wujud fisik yang mengelilingi kehidupan manusia. Pandita hidup dengan alur pikir dari kepala ke atas sampai menembus langit. Sementara itu, satria hidup dengan berpatokan pada dada yang menjembatani kepala dan perut. Satria berulang-alik memahami dua spektrum fisik-batin yang berbeda dan memandang keduanya sama-sama penting untuk diwujudkan. Kehidupan fisik membutuhkan materi untuk mengejar yang batin. Keduanya signifikan bagi manusia. Kategori terakhir ialah sudra. Sudra tidak berarti miskin atau bahkan fakir karena kelompok ini juga dapat dalam keadaan kaya raya. Sudra adalah manusia yang orientasi berpikirnya dikuasai perhitungan untung-rugi bagi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kategori ini berpikir dalam batas perut ke bawah.
Dalam penjelasan itu, satria merupakan sosok yang pantas mengemban tugas mengelola kehidupan karena ia berada di posisi paling mampu mengubah nilai-nilai transendental menjadi kemaslahatan hidup, sekaligus mentransendensi kehidupan. Ia berada di antara langit dan bumi. Dalam tradisi kekeratonan Jawa, pada suatu masa pernah berlaku larangan bahwa kelompok satria tidak boleh berdagang. Larangan ini tidak dipandang sebagai perampasan hak setiap orang melakukan sesuatu, melainkan pemberian batas yang menjaga laku pengelolaan dan pengayoman masyarakat dengan semangat pengabdian. Larangan ini juga menjauhkan keraton dari cara berpikir untung-rugi untuk menjaga kemurnian batin. Hal ini dilakukan agar mampu menangkap nilai kudus ajaran Tuhan dan menerjemahkannya menjadi kemaslahatan di dunia. Larangan itu pun untuk memastikan pemimpin memiliki kualitas satria pinandhita sinisihan wahyu.
Untuk dapat memahami konteks tersebut di masa kini, kita dapat membacanya melalui konteks kontemporer dari konsep kepemimpinan Jawa itu diterjemahkan secara tepat oleh Emha Ainun Najib (2008). Emha menulis, ksatria mampu memimpin dengan memahami peta masalah, piawai manajemen, dan professional. Ksatria pun memiliki kapasitas pinandito atau kapasitas spiritual, yakni berani dan ringan menekan nafsu keduniaan di dalam dirinya, bahkan sinisihan wahyu yang artinya tindak-tanduk kepemimpinannya dibimbing oleh petunjuk Tuhan. Dengan kata lain, kualitas satria pinandhita sinisihan adalah seorang pemimpin yang sudah mencapai rumangsa melu handarbeni (rasa kepemilikan komunal) dan telah meninggalkan rumangsa melu handuweni (rasa kepemilikan individu) bila kita menggunakan panduan kepemimpinan transformatif dari Mangkunegara I.
Baca juga: #janganjadidosen?
Hari ini kita tiba di wolak-walik ing jaman (bolak baliknya jaman). Semua menjadi sudra pada waktunya. Pandita memperlakukan ilmu dan kebenaran dalam semangat transaksional yang menguntungkan dirinya, sama seperti sang satria yang menggunakan kewenangan pengelolaan untuk dirinya sendiri. Menumpuk keuntungan dan kuasa hanya untuk kepentingan pribadi. Nalar ekonomi telah memangsa nalar berilmu, beragama, dan bernegara. Robert Reich (2008) mengistilahkan kondisi demikian dengan supercapitalism. Kompas nilai yang menggerakkan hidup hanya tinggal satu: apa yang menguntungkan bagiku.
Demokrasi diciptakan setara untuk semua orang, tanpa menyandang status tertentu yang membatasi kesempatan. Hal ini dilakukan untuk kemaslahatan semua. Apabila semua orang tetap mawas diri, dengan sadar ia tidak mengambil putusan persoalan yang menyangkut kebenaran dan kewenangan dengan pertimbangan untung rugi semata. Hal ini karena kebenaran dan kewenangan milik semua orang dan tidak semestinya diperlakukan sebagai pertukaran mata uang. Kemerdekaan dalam kesetaraan hanya akan menghasilkan kemudaratan apabila kita tidak bersama-sama merasakannya. Semua orang merasa mampu dan berhak mengurus sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya, terlebih hal yang dimediasi oleh internet dan media sosial. Setiap manusia tergoda menjadi rumangsa bisa (merasa bisa), alih-alih bisa rumangsa (bisa merasakan). Tidak mengherankan apabila kondisi matinya kepakaran (the death of expertise), seperti yang ditulis Tom Nichols (2018), berkembang. Pada titik ini, Petruk sebaiknya tetap menjadi punokawan, tanpa perlu menjadi ratu, karena jalan Petruk mewujudkan kemaslahatan bagi sesama adalah dengan menjadi punokawan. Dengan demikian, sikap tahu diri menjadi penting sehingga tindakan membohongi kemampuan diri sendiri sekadar untuk memuaskan hasrat menumpuk keuntungan tidak terjadi. Himbauan Soekarno (dalam Latif, 2009: 23) “marilah kita awas, jangan sampai rakyat-jelata Indonesia tertipu oleh semboyan ‘demokrasi’ …, yang akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka oleh kaum borjuis yang bergembar-gembor ‘demokrasi’-kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi sebenarnya hanya mencari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri, keuntungan sendiri!” ini semakin menemukan relevansinya menghadapi perkembangan sosial politik yang dipenuhi muslihat dan inkompetensi.
Demokrasi yang termediasi oleh media komunikasi memberi kesempatan untuk mengaburkan ketidakmampuan atau ketidakjujuran pengelolaan itu melalui bahasa. Zen R. S. dalam cuitan Twitter-nya menggambarkan dengan tepat bahwa “untuk setiap aib yang tidak mungkin diakui, bahasa Indonesia menyediakan jalan keluar yang menyebalkan: oknum”. Kata oknum adalah bentuk pengalihan kesalahan kepada individu tertentu dan membersihkan unsur sistematis dari setiap kesalahan yang dilakukan. Sayangnya, kata oknum tidak sendiri karena kata mafia melengkapi sisi kesalahan terstruktur yang tidak mungkin ditimpakan pada individu, apalagi pada kesalahan yang bersifat makro.
Baca juga: Eksil, 1965, dan Arah Politik Permaafan Kita
Kriteria individu seperti apa yang cukup logis untuk ditimpakan pada seseorang yang melakukan kesalahan yang berdampak luas dan menjalar? Individu seperti apa yang mampu melakukan transaksi ekspor minyak goreng yang mampu membuat kelangkaan di dalam negara dan kemudian menjalar pada penghapusan harga eceran tertinggi? Pada titik ini, kata mafia hadir menggantikan oknum. Mafia memiliki unsur kognitif konspiratif sehingga meski dia beroperasi sistematis, tetapi sulit dijamah. Kata mafia memaksa kita menjadi maklum jika negara tidak mampu menunjuk hidung orang yang menyengsarakan rakyat. Masalahnya, kita terlampau lumrah dengan istilah mafia migas, mafia beras, mafia peradilan, mafia tanah, mafia minyak goreng, dan mafia beras. Apakah mafia-mafia ini menguasai banyak sektor dan sendi bernegara?
Menafsirkan episode wayang Petruk dadi ratu memang dapat dilihat dari dua sisi: pertama dari sudut pandang status, dan kedua dari sudut pandang peran. Pada sudut pandang pertama, kita melihat bagaimana status kepemimpinan rentan digantikan oleh orang dengan status yang lebih rendah. Dalam konteks demokrasi, hal ini sangat dimungkinkan karena status pemimpin dapat diakses oleh siapa saja. Pendekatan kedua, menurut hemat kami, memiliki level yang lebih dalam karena bukan lagi siapa yang mendapatkan status apa, tetapi lebih pada bagaimana orang memerankan status tertentu. Cerita ini menunjukan bahwa Petruk, si rakyat jelata yang naik tahta menjadi raja, akhirnya membawa kekacauan karena adanya mal-manajemen. Hal ini terjadi karena Petruk, saat menjalani perannya sebagai raja, masih bersikap sama ketika ia menjadi rakyat jelata yang hanya bisa kaget atau marah melihat kerusakan yang terjadi. Dia lupa bahwa sekarang ia memegang palu yang dapat digunakan untuk memperbaiki sesuatu. Akhirnya, sebaik apapun niat dan usaha Petruk, ia tetap terperosok pada keadaan yang kacau juga. Hal ini menunjukan bahwa yang penting dalam mengubah suatu kekacauan bukan hanya mengubah status seseorang saja, melainkan juga kesesuaian antara peranan dan kemampuan. Singkatnya, seorang pemimpin atau rakyat jelata tidak akan memperbaiki keadaan hanya dengan bertukar posisi.
Masalahnya, di negara kita, orang masih sering lupa akan peran mereka. Seorang yang menjadi pemimpin seharusnya membuat kebijakan untuk kepentingan orang banyak, tetapi ia yang justru ia berperan layaknya mafia yang menggunakan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri atau kelompoknya. Hal ini seperti seorang agamawan yang menjaga moral justru berperan sebagai pedagang yang mengobral dagangan untuk melipatgandakan kapital; Atau seorang menteri yang seharusnya mengatur kesediaan minyak justru menjadi agen minyak ke luar negeri untuk keuntungannya sendiri. Fenomena tersebut tidak akan terjadi apabila mereka semua memahami makna cerita Petruk dadi ratu, yaitu ketika tatanan yang jungkir balik membawa kesengsaraan bagi semua orang.
**) Artikel ini pertama kali terbit pada Juni 2022 di situs pmb.lipi.go.id yang saat tulisan ini diterbitkan ulang sudah tidak aktif. Redaksi sudah mendapat izin penulis untuk menerbitkan artikel ini. Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.