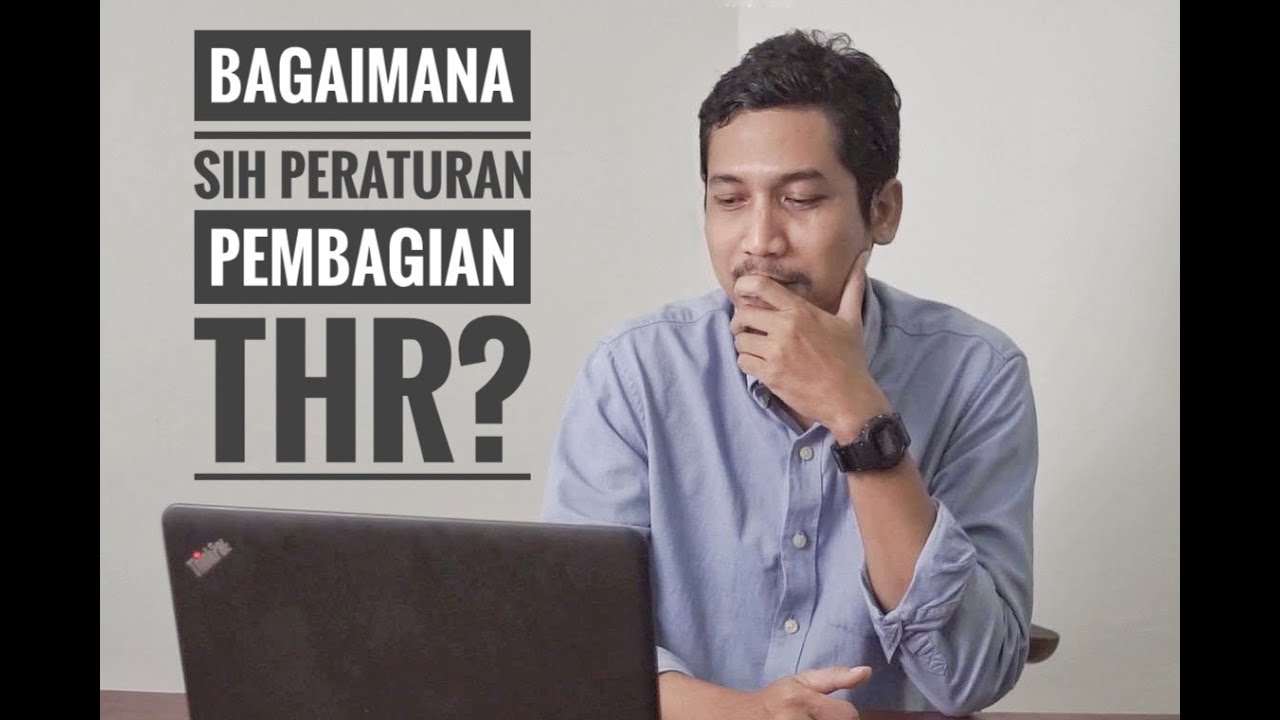Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
Oleh: Detta Rahmawan, Universitas Padjadjaran; Justito Adiprasetio, Universitas Padjadjaran, dan Kunto Adi Wibowo, Universitas Padjadjaran
Unggulnya pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024 yang lekat dengan dendang “Oke Gas-Oke Gas” ataupun “joget gemoy” menandai kegandrungan kita dengan hiburan politik (politainment) di media sosial.
Prabowo-Gibran tak sendirian. Pemilihan umum kali ini juga diramaikan dengan adu gimik senada dari para pesaingnya maupun kandidat anggota parlemen guna memikat pemilih.
Beragam narasi itu, sialnya, malah membuat isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup warga, terutama generasi muda, terlempar dari arena perbincangan politik. Padahal, berbagai survei secara konsisten memperlihatkan bahwa isu iklim dan lingkungan hidup menjadi perhatian dari banyak anak muda dan pemilih pemula. Banyak pula orang Indonesia (73%) yang merasa “cemas” dan “sangat cemas” dengan perubahan iklim.
Setelah ingar-bingar pemilu surut, penting bagi kita untuk semakin serius menyoroti isu iklim dan lingkungan. Selagi momentumnya masih hangat, kita perlu mendudukkan dua isu di atas sebagai dasar untuk mengawal perumusan program kerja presiden maupun politikus terpilih.
Partisipasi di tengah risiko demokrasi
Pemilu adalah awal—bukan akhir—bagi kita untuk mengembalikan diskusi politik supaya lebih berisi. Pasalnya, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan para kandidat terpilih, detail isu iklim dan lingkungan akan dibahas dalam pembicaraan tentang kebijakan, regulasi, dan arah prioritas program-program pemerintah selanjutnya.
Di titik inilah, kita perlu memahami bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan tidak akan selesai atau lenyap seusai trending di media sosial.
Kita perlu lebih banyak bersuara agar kebijakan iklim dan lingkungan berada di jalur yang benar, setidaknya cukup untuk menahan laju pemanasan Bumi di angka 1,5°C, polusi, dan kehilangan biodiversitas.
Memang ada beberapa kekhawatiran soal kembalinya rezim otoritarian Indonesia pada kepemimpinan Prabowo-Gibran nanti. Namun, kekhawatiran tersebut masih terlalu dini.
Berbagai survei memperlihatkan bahwa masyarakat kita masih memiliki persepsi positif terhadap praktik demokrasi. Indonesianis dari Chatham House Inggris, Benjamin Bland, juga mengatakan bahwa cukup sulit membayangkan adanya perubahan drastis menuju pemerintahan otoritarian non-demokratis dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, terlepas dari besar-kecilnya peluang, masih ada jalan bagi kita untuk turut serta membentuk kebijakan dan aksi iklim di Indonesia.
Partisipasi perlu di-gas
Riset kami yang bertajuk mengomunikasikan partisipasi sebagai isu publik menggarisbawahi praktik partisipasi warga dengan ruang dan kebebasan yang memadai sebagai hak yang perlu dijaga. Makna partisipasi jangan sampai menjadi sekadar proses administratif-simbolik.
Misalnya seperti saat pemilu, suara warga selalu diminta tapi kemudian tidak didengarkan. Atau, dalam kegaduhan soal hilirisasi nikel. Alih-alih memberi panggung untuk elit politik yang mengatakan kritik hilirisasi sebagai halusinasi, kita perlu lebih serius membahas warga sekitar pabrik nikel yang masih terjebak kemiskinan.
Menarik perhatian masyarakat terhadap isu iklim dan persoalan lingkungan memang tidak semudah meraup likes di media sosial. Oleh karena itu, kita perlu memiliki lebih banyak panduan praktis agar komunikasi isu iklim dan lingkungan hidup, terutama dari perspektif masyarakat sipil dan mereka yang terdampak, bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Beberapa dokumen seperti panduan komunikasi untuk politisi membicarakan isu perubahan iklim, panduan komunikasi kebijakan transisi energi, hingga metode komunikasi perubahan iklim kepada masyarakat Indonesia, perlu menjadi rujukan.
Kita juga perlu mengapresiasi gerakan anak muda seperti Bijak Memilih yang telah membantu banyak pemilih pemula semakin melek politik. Inisiatif ini juga perlu dikembangkan agar pemilih pemula dapat melihat keterkaitan isu iklim, lingkungan hidup, dan politik.
Begitu pula dialog langsung seperti “desakanies” dan “demokr(e)asi” oleh kandidat Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di berbagai kota saat masa kampanye silam. Politikus dapat mengadopsi praktik keduanya, misalnya saat mendatangi konstituen di suatu lokasi, untuk menjaring aspirasi langsung seputar persoalan iklim, dan lingkungan. Hal ini dapat menjadi penyegaran kala berbagai acara kampanye partai politik sering bersifat searah.
Kita juga perlu mengingatkan masyarakat tentang pentingnya oposisi kritis. Warga perlu diajak untuk memiliki persepsi yang sama bahwa partisipasi mereka sangat krusial dalam demokrasi.
Untuk organisasi masyarakat sipil (OMS) dan gerakan warga, mengkritik gimik tidak berarti menghindari tren dan cara bertutur di media sosial. Ruang media sosial justru harus digeluti lebih serius, dengan tetap melibatkan warga, bukan menjadi medium khotbah berjarak semata.
OMS dan gerakan masyarakat sipil perlu menyadari kekurangan bersama dalam kontestasi isu iklim dan lingkungan dalam wacana politik lima tahun terakhir. Pemilu telah usai, dan kita tidak bisa terus “joget gemoy” saja, saat Bumi semakin panas membara.![]() []
[]
***
Detta Rahmawan, Lecturer in Communication Science, Universitas Padjadjaran; Justito Adiprasetio, Lecturer, Universitas Padjadjaran, dan Kunto Adi Wibowo, Associate professor, Universitas Padjadjaran