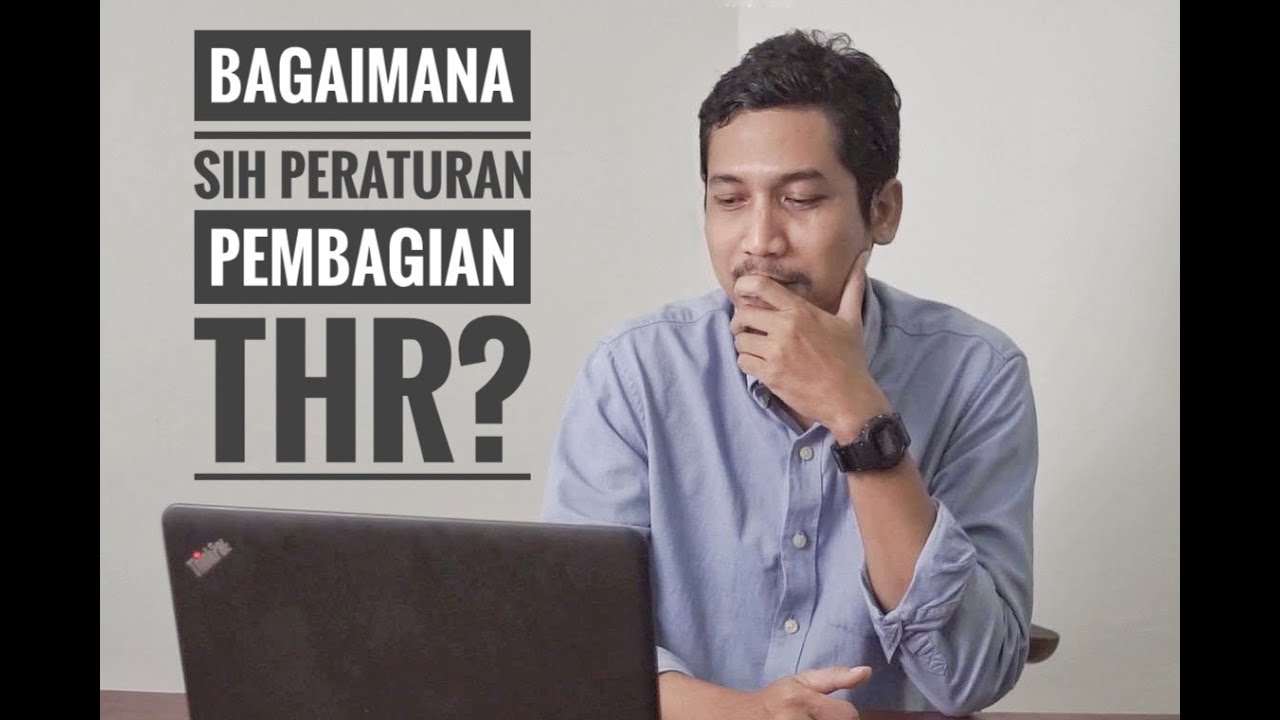Oleh: Devi Anggar Oktaviani
“The wonderful things in life are the things you do, not the things you have.”
Ditutup dengan kutipan dari seorang pendaki gunung termasyhur asal Italia, Reinhold Messner, film dokumenter “Negeri Dongeng” garapan sineas Anggi Frisca sukses menarik animo penggemar kegiatan alam bebas. Diputar serentak pada Kamis 26 Oktober 2017, salah satu studio bioskop di Jakarta Selatan, tempat saya menonton, sudah terisi penuh pukul 21.25 WIB.
Sebelum nonton, saya sudah membayangkan akan “disiksa” oleh pemandangan alam, lansekap gunung, bukit, dan hamparan awan; disiksa dengan kembalinya memori-memori mendaki di masa lalu; disiksa realita entah kapan saya akan mendaki gunung lagi; disiksa kerinduan akan gunung yang bahkan belum pernah saya lihat langsung.
Namun, ternyata Negeri Dongeng bukan hanya tentang keindahan dan kengerian gunung, melainkan juga tentang pertemanan, kebudayaan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di kaki gunung yang jauh dari hiruk pikuk Ibu Kota. Ini tentang alam dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya menjadi sesuatu yang menarik di mata warga urban, juga tentang ironi Indonesia yang kaya akan hasil bumi, tetapi justru menjadi negeri yang tidak mampu untuk mengolah kekayaannya sendiri.
Sampai di situ saya terdiam. Pertanyaannya sederhana saja: Lalu setelah dokumenter Negeri Dongeng ini apa yang akan terjadi dengan dunia pendakian Indonesia? Apakah alam dan gunung-gunung Indonesia akan baik-baik saja? Berapa banyak yang sadar dan mulai belajar? Berapa banyak orang-orang yang berpikir untuk menggapai puncak-puncak tertinggi Indonesia? Pecinta alam ataukah perusak alam yang mengotori gunung dengan sampah dan laku vandalisme?
Sebagai gunung favorit banyak orang, Semeru adalah salah satu gunung yang menjadi sasaran egoisme para penakluk ketinggian. Masalah sampah tentu saja menjadi sorotan utama. Menurut data Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru, khusus untuk kawasan gunung Semeru menghasilkan 1,5 ton sampah setiap bulan.
Baca juga : Perempuan dan Sepeda Motor
Masalah pendakian ternyata tidak hanya berhenti di persoalan sampah saja. Informasi tentang pendaki yang tersesat, cedera, hingga meninggal juga sudah banyak terjadi. Sejak kematian Soe Hok Gie dan Idhan Lubis 47 tahun silam, sekaligus sebagai dua pendaki pertama yang meninggal di gunung Semeru kasus serupa juga terus berulang.
Hingga 2009, sebanyak 28 pendaki meninggal dan 3 orang dinyatakan hilang dalam pendakian. Dan pada 2016 angka tersebut terus meningkat, setidaknya lebih dari 30 orang diberitakan meninggal di gunung Semeru dengan berbagai penyebab.
Sementara itu, menurut data tidak resmi dari komunitas pendaki gunung disebutkan sejak Juli 2013 hingga Oktober 2017 terdapat 88 pendaki dalam dan luar negeri meninggal di gunung-gunung Indonesia. Data terakhir ditutup oleh kabar meninggalnya pendaki asal Jakarta di gunung Carstenz, Papua pada awal Oktober lalu karena mengalami hipoksia (kekurangan oksigen) dalam perjalanan turun.
Baca juga : Kapan Kita Layak meng-“cancel” Seseorang Maupun Karyanya Akibat Perilaku Tercela?
Pada intinya mendaki bukanlah kegiatan mudah dan instan. Dalam pendakian—pun dalam segala hal—kita bertanggung jawab tidak hanya pada diri sendiri, melainkan juga pada orang lain, dan tentu saja alam. Bertanggung jawab atas setiap hal yang dilakukan, maupun dalam mengambil keputusan yang berlandaskan kesadaran. Kesadaran untuk menjaga dan menghargai alam, karena alam juga memiliki hak untuk bebas dari adanya hama bernama manusia kota.
Meski pendakian sudah menjadi bagian dari pariwisata, mendaki gunung bukanlah kegiatan impulsif. Apalagi ajang ketenaran dan pembuktian eksistensi diri demi pujian. Pendakian lebih tinggi dari itu. Pendakian adalah perenungan—perjalanan ke dalam diri.
Oktober 2017
*Tulisan ini semula terbit di blog pribadi penulis. Penulis adalah SEO Editor.