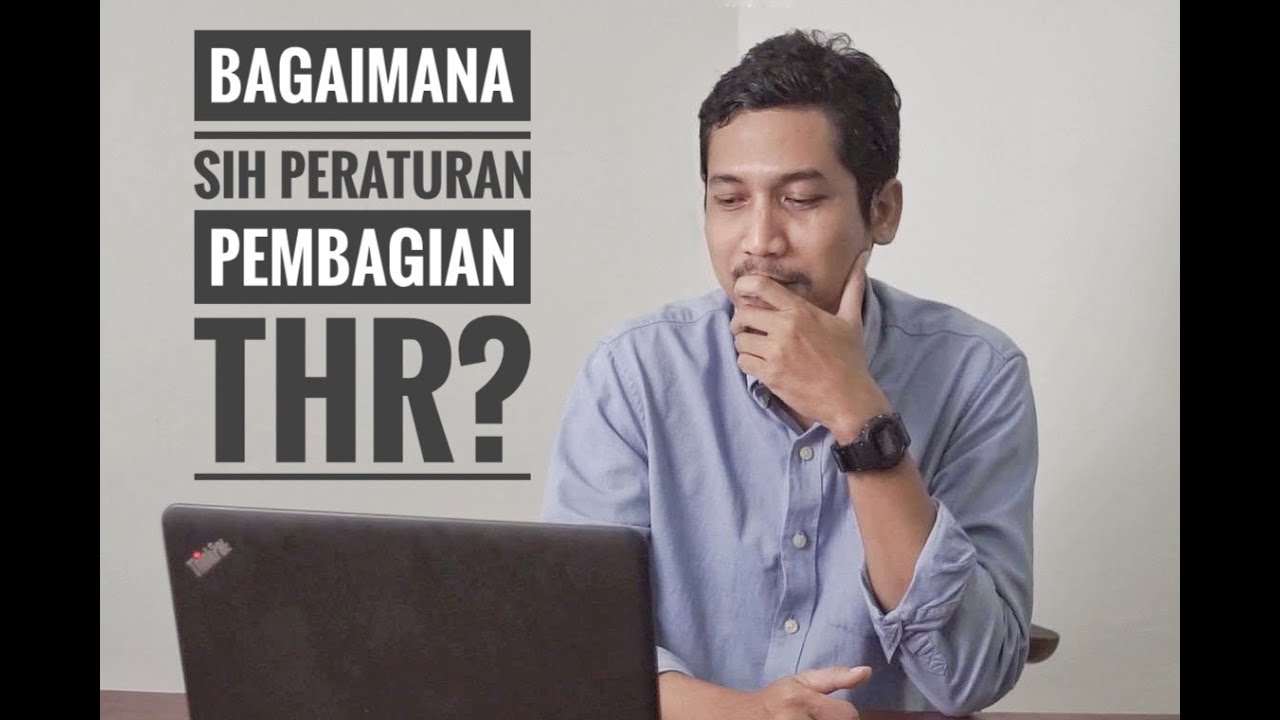Oleh : Ahmad Rahma Wardhana, Universitas Gadjah Mada
Istilah transisi energi begitu populer di media massa, seminar, diskusi, dan perbincangan masyarakat. Transisi energi adalah usaha kita untuk beralih dari pemakaian energi fosil ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Sebagian besar dari kita mungkin bertanya: apa maknanya, bagaimana melakukannya, dan tentu saja, apa untungnya buat kita jika kita semua jika kita benar-benar melakukannya.
Tulisan ini menjelaskan tiga hal mendasar tentang transisi energi.
1. Transisi energi adalah mitigasi perubahan iklim
Transisi energi merupakan satu dari sekian banyak bentuk mitigasi atau usaha meredam perubahan iklim.
Sedangkan perubahan iklim merupakan akibat dari naiknya suhu rata-rata permukaan bumi (pemanasan global) dalam setidaknya dalam durasi 30 tahun.
Pada mulanya, menghangatnya permukaan Bumi adalah sebuah kewajaran. Normal. Bahkan kebutuhan. Tanpa paparan sinar matahari yang menghangatkan, hewan, tumbuhan, dan manusia tidak bisa tumbuh.
Jika energi panas sinar matahari memancar dari sumbernya dengan kekuatan 100%, maka ia akan terbagi-bagi: dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh awan dan atmosfer 23%, diserap atmosfer 23%, diserap permukaan bumi 47%, dan dipantulkan oleh bumi kembali ke luar angkasa 7%.
Skenario normal ini merupakan bagian dari earth’s energy budget atau anggaran energi bumi, sebuah neraca energi yang masuk ke bumi dan yang keluar dari bumi ke luar angkasa.
Semua berubah ketika revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, saat era produksi massal menjadi tren.
Sejak itu konsumsi energi meningkat di berbagai sektor kehidupan yang didapatkan dari membakar kayu, minyak bumi, gas, dan batu bara (karena itu mereka disebut bahan bakar). Bahan bakar itu merupakan senyawa berbasis unsur hidrogen (H) dan karbon (C), yang meninggalkan limbah di atmosfer setelah dibakar. Kita menyebutnya emisi karbon.
Apa yang terjadi saat dan setelah emisi karbon memenuhi atmosfer kita?
Neraca anggaran energi bumi kita tak lagi seimbang. Atmosfer yang memiliki kemampuan menyerap dan memancarkan energi menjadi penyimpan panas yang semakin baik. Hangatnya matahari yang seharusnya hanya berlangsung saat matahari bersinar saja, justru menghangatkan bumi sepanjang 24 jam penuh karena disimpan oleh atmosfer.
Energi panas permukaan bumi yang seharusnya terpancar ke luar angkasa, malah terjebak di atmosfer.
Dalam istilah sains, atmosfer kita yang dipenuhi emisi karbon juga sering disebut Gas Rumah Kaca (GRK) karena efeknya yang menjebak panas bagaikan rumah kaca untuk lahan pertanian itu.
Planet kita tidak lagi menghangat, tapi memanas sejak beberapa dekade terakhir. Bahkan kini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mulai frustasi dengan lambatnya upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dia pun mengenalkan istilah baru: pendidihan global.
2. Mengapa butuh transisi energi? Bagaimana caranya?
Mengapa pilihannya adalah transisi energi?
Jawaban pertama, bukti ilmiah temuan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) terbaru menunjukkan bahwa sumber GRK terbesar berasal dari sektor energi (34%). Lalu disusul industri (24%), kegiatan di sektor pangan, kehutanan, dan alih fungsi lahan (22%), dan transportasi (15%) serta bangunan (6%).
Maka, upaya transisi energi merupakan ikhtiar mengendalikan 49% sumber GRK (energi dan transportasi).
Jawaban kedua, transisi energi bukanlah silver bullet (obat mujarab lengkap) yang mampu menyelesaikan persoalan pendidihan global dan perubahan iklim secara serta-merta. Upaya itu hanya salah satu bentuk ikhtiar.
Saat kita melakukannya saja, perubahan iklim tidak otomatis tertanggulangi, apalagi kalau tidak melakukannya!
Lalu, bagaimana melakukan transisi energi?
Nah, di titik ini jawabannya mulai ruwet karena urusannya sangat kompleks.
Transisi energi di bidang transportasi misalnya, berarti mengubah jenis bahan bakarnya: dari minyak bumi (bensin, solar, avtur), ke bahan bakar lain, seperti bahan bakar organik (bioenergi) yang diperoleh dari makhluk hidup.
Bioenergi di Indonesia sedikitnya punya tiga tantangan. Pertama, kita cenderung menggunakan tanaman sawit untuk mengurangi pemakaian solar.
Sayangnya, perkebunan kelapa sawit dibangun dengan fondasi yang buruk. Seperti mengubah hutan yang tanamannya beragam-–dengan segudang jasa ekologisnya–-menjadi hutan yang tanamannya seragam. Dalam prosesnya, perusahaan sawit kadang kala membakar lahan gambut yang justru menambah GRK di angkasa.
Kedua, bioenergi berbasis jagung dan singkong untuk mengurangi penggunaan bensin. Ini berarti akan memicu persaingan fungsi lahan antara jagung dan singkong sebagai tanaman pangan (manusia) dan pakan (ternak) versus sebagai tanaman energi.
Ketiga, bioenergi berbasis ganggang (microalgae) masih membutuhkan riset yang panjang untuk bisa efisien.
Ada juga opsi lain, yaitu penggantian mesin yang berbasis pembakaran menjadi listrik. Pada titik ini, kekusutannya bertambah.
Meskipun kendaraannya tak lagi membakar bensin atau solar, ketika mengisi baterai kendaraan, kita menancapkan kabel kendaraan pada listrik yang berasal dari pembakaran batu bara.
Bagaimanapun, lebih dari setengah pembangkit listrik Indonesia (54,94%) merupakan ajang penambangan dan pembakaran bahan bakar fosil bernama batu bara.
3. Kunci transisi energi: listrik
Pembahasan kita sekarang menukik pada persoalan listrik.
Listrik adalah sebuah produk yang paling dicari semua orang. Lampu rumah, rice cooker dan alat dapur, lemari es, televisi, radio, AC, telepon genggam, laptop dan komputer, lift kantor, dan beberapa jenis kereta membutuhkan listrik. Begitu pula dengan kegiatan kita sehari-hari: pendidikan, kesehatan, hiburan, usaha kecil, industri besar, dan sebagainya.
Upaya transisi energi di sektor listrik berarti bagaimana caranya mengurangi 54,94% pembangkit batu bara.
Ada solusi, misalnya dengan co-firing. Maksudnya mengganti sebagian batu bara yang dibakar di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan pelet kayu atau bahan berbasis makhluk hidup lainnya (disebut biomassa).
Tantangan dari solusi ini serupa dengan sawit: ada potensi penggunaan lahan yang merusak keragaman hutan, ataupun persaingan lahan antara urusan pangan dengan urusan energi.
Sementara solusi energi terbarukan seperti air, angin, dan surya, juga menghadapi banyak persoalan. Energi air dinilai tidak ramah secara ekologis karena, ketika skalanya besar, pembangunan bendungannya bakal menenggelamkan beberapa ekosistem.
Angin dan surya diterpa persoalan pasokan yang tidak konstan (disebut intermitensi). Angin tak selalu berhembus 24 jam. Durasi sinar matahari di Indonesia hanya efektif 4-5 jam setiap harinya.
Bahkan energi surya juga diancam oleh bayang-bayang ketergantungan impor. Pasalnya, kita tak punya industri manufaktur yang memproduksi komponen utamanya. Ketika industri manufaktur mencoba masuk (industri nikel dan baterai), kita tahu persis bagaimana efek lingkungannya tak diawasi dengan baik oleh otoritas Indonesia.
Optimisme transisi energi
Banyak orang yang bekerja di sektor energi selama ini merasa pusing ketika mengelola kerumitan tersebut. Itu baru masalah teknis.
Dari perspektif kebijakan pemerintah, termasuk sikap dan perilaku perusahaan energi pelat merah, daftar masalahnya tak kalah panjang.
Namun, kita harus optimistis bahwa transisi energi itu mungkin dilakukan.
Tantangan-tantangan tersebut seharusnya mendorong kita semua (terutama pelaku industri bahan bakar fosil!) untuk mulai peduli pada urusan transisi energi.
Kita harus mencari solusi terbaik yang seimbang antara perspektif teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Itu memang tidak mudah, tapi mungkin.![]()
Ahmad Rahma Wardhana, Peneliti dan Mahasiswa Doktoral, Universitas Gadjah Mada
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.