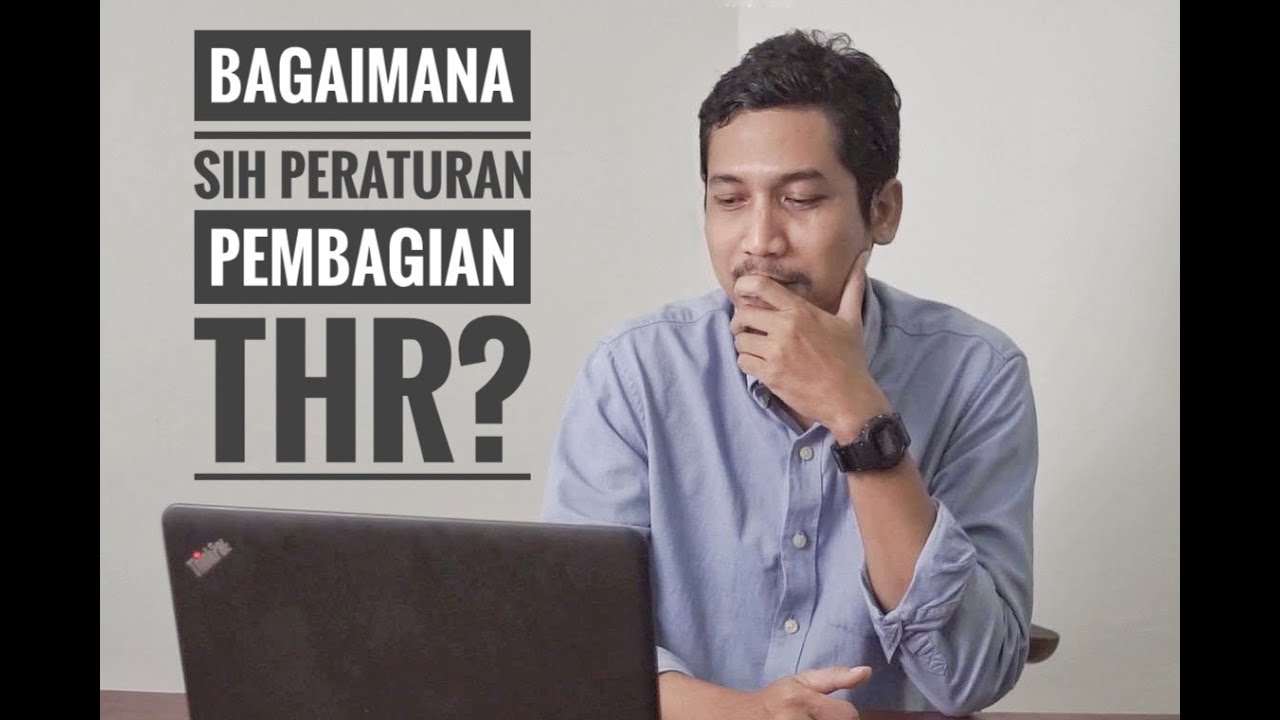Ini merupakan arsip Kompas Minggu, 5 Januari 1992 di halaman 10. Tulisan ini mengurai pandangan seniman dan sastrawan Remy Sylado mengenai lagu Indonesia Raya. Ia menjabarkan bukti mengenai kasus hak cipta lagu kebangsaan Indonesia karya WR Supratman tersebut.
Kerabat kerja ProPublika.ID menerbitkan arsip ini untuk mengenang almarhum Remy Sylado yang berpulang pada 12 Desember 2022. Selain itu, penerbitan arsip ini untuk tujuan pendidikan.
SUPRATMAN “INDONEES INDONEES”, DAN KASUS HAK CIPTANYA
Oleh: Remy Sylado
Arsip Kompas Minggu, 5 Januari 1992
TULISAN Kaye A. Solapung (Kompas, 22 Desember 1991) bagus. Ia berani mempertanyakan lima soal yang tidak dimengertinya dari tulisan saya tentang Supratman dan karyanya. Mengingat tulisannya itu juga tersesat karena hanya dialas oleh prasangka yang dianggapnya kebenaran, maka amat perlu ditanggapi lagi. Lima pertanyaannya akan saya jawab dengan sembilan uraian.
Supratman lahir 9 Maret 1903, yang menurut hari pasaran Jawa jatuh pada Wage. Pada usia 11 tahun (1914), ia dibawa ke Makassar oleh W.M. van Eldik, Administrateur Gewapande Politie. Agar bisa diterima di Europese Lagere School, Eldik memasang namanya jadi Rudolf. Tetapi, kesempatan belajar di sekolah Belanda itu hanya singkat, sebab ketahuan, ia bukan sedarah dengan Eldik dan terpaksa dikeluarkan. Ia pindah ke sekolah Melayu, sambil belajar musik dan kursus bahasa Belanda. Tahun 1919, ia lulus ujian dengan diploma Klein Ambtenaar Examen, dan berkesempatan melanjutkan ke Normaal School untuk menjadi guru.
Masih belajar, ia boleh mengajar. Ia berhenti mengajar karena akan dipindahkan ke Singkang yang waktu itu rawan. Maka ia pun bekerja sebagai klerk di Firma Nedem, meski tak lama. Ia pindah ke kantor advokat terpandang, Mr. Schulten sebagai klerk. Waktu itulah, 1920, ia mendirikan dan memimpin band jazz “Black and White“, salah seorang anggotanya adalah iparnya sendiri, Eldik.
Oleh suatu hal, tahun 1924 ia pindah ke Surabaya, tinggal di rumah kakaknya Roekinah Soepratirah. Lalu ia pindah lagi ke Cimahi, bersama ayahnya, Djoemeno Senen yang sersan KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger). Selama itu, hidupnya getir. Pekerjaannya, sementara sebagai juruwarta Kaum Muda di Bandung, tetapi bosan, lalu kembali cari kerja sebagai pemain musik.
Bermusik di Bandung pun tak lama. Pada 1925, ia berangkat ke Jakarta, jumpa pada Parada Harahap dan bersama-sama mendirikan kantor berita Alpena. Kantor ini tutup, lalu bekerja sebagai wartawan Sin Po, dan hidupnya tetap susah. Ia diam di sebuah rumah reyot di perkampungan miskin di Rawamangun. Namun, sebagai wartawan, ia banyak berkenalan dengan tokoh Pergerakan Nasional. Sumber otentik tentang pribadinya, selengkapnya dapat diperiksa dalam memoar yang ditulis oleh saudaranya sendiri, Oemar Kasansengari, Sejarah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan W.R. Soepratman Pentjiptanja (PD Pertjetakan Grafika Karja, Surabaja, tanpa tahun).
***
SEBELUM Kongres Pemuda, Supratman menulis surat kepada Bung Karno, dengan mengirim rekaman Indonees Indonees, untuk kiranya dapat diperdengarkan di kongres itu nanti. Ketika lagu itu diperdengarkan, kongres menyambut antusias dan setuju menjadikannya sebagai lagu perjuangan, disusul saran melakukan perbaikan menyangkut nada dan irama yang sama dengan Lekka Lekka.
“Een lied, zo krachtig, dat de vonken ervan afvliengen,” ujar Bung Karno yang diulangi lagi dalam kepentingan lain saat mengomentari lagu Untuk Indonesia Raya karya Marno. (Lihat siaran RRI Jakarta pada Pidato Radio V, 7 Januari 1951). Sejauh itu, belum ada ketentuan mengenai tata tertib mendengar dan menyanyikannya, kecuali pada 1929, dalam kongres PNI ke-2 di Gang Kenari, Jakarta, Bung Karno meminta hadirin berdiri.
Selama 14 tahun setelah itu, lagu ini dilarang Belanda, sampai masuknya Jepang. Waktu itu, kata-kata yang digunakan Supratman untuk refrain, memang Indonees (Indones), yang jatuh suku kata pada tel, yaitu Indones, Indones, merdeka, merdeka/ Tanahku, negriku, yang kucinta.” Karena larangan Belanda untuk “merdeka”, maka Bung Karno menyarankan mengubahnya menjadi “Indonesia Raya, mulia, mulia / Tanahku, negriku, yang kucinta”. Setelah ditimbang-timbang, pada zaman Jepang, lirik ini diubah lagi menjadi “Indonesia Raya, merdeka, merdeka / Tanahku, negriku yang kucinta.”
Soal penggunaan Indones atau Indonees, sebetulnya bukan hanya waktu Indonesia masih dijajah Belanda, tetapi juga setelah Proklamasi, manakala lagu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Teks Inggris “Inones, Indones, noble land, noble land / Oh our soul and our land Indonesia.” dan teks Jermannya “Indones, Indones, lieb Vaterland / Glorreiches Vaterland das ich liebe.”
***
SEJAK disepakati lagu ini menjadi lagu perjuangan dan berlanjut menjadi anthem Nasional, memang telah beberapa kali dilakukan pembenahan, dengan atau tanpa panitia khusus, karena dianggap banyak kelemahannya. Masalah pelik yang diajukan kepada Bung Karno menyangkut delapan bar yang sama dengan Lekka Lekka itu. Pembenahan secara resmi dengan sebuah panitia khusus, pertama kali dibentuk 8 September 1944, diketuai langsung oleh Bung Karno, dengan anggota Ki Hadjar Dewantara, Achiar, Soedibjo, Damawidjaja, Koesbini, KHM Mansjoer, Muhammad Yammin, Sastromoeljono, Sanoesi Pane, Simandjoentak, Achmad Soebardjo, dan Oetojo.
Panitia menetapkan empat ketentuan, yaitu (1) jika dinyanyikan satu kuplet, ulangannya dilakukan dua kali, jika tiga kuplet ulangannya satu kali, tetapi pada kuplet ketiga ulangannya dilakukan dua kali; (2) pada upacara bendera ukuran cepatnya harus 104, dan waktu berbaris harus 1-2-120; (3) kata semua diganti sem’wanya dengan menambah not do; (4) istilah “refrain” diganti jadi “ulangan”.
Toh ketetapan ini masih kurang dan perlu pembenahan. Oleh sebab itu, pada 1948 Bung Karno meminta panitia membenah ulang, namun urung berhubung terjadi Clash II, dan konsentrasi bangsa pada perang, seperti dipidatokan Bung Karno pada 17 Agustus 1948. “Kita binasakan, kita ledakkan, kita bakar habis-habisan; wij hebben niets te verlingen doch alles….”.
Sungguh pun begitu, ditemukan perubahan dalam catatan partiturnya sebagai: marcia con bravura, 4/4, MM = 90 – 100, Do = G. Kemudian melalui pembenahan yang dilakukan sepuluh tahun setelah itu, sesuai PP No 44, 26 Juni 1958, lagu ini menjadi = 104, di marcia, 1 = g.
Baca juga: Mengenang Ignas Kleden #1: Simbolisme Cerita Pendek
Selama itu, sebelum PP No 44, 1958, tidak berarti tiada kritik atasnya. Dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, beredar buku Musik di Indonesia (J.A. Dungga dan L. Manik, Balai Pustaka, Jakarta, 1952). Di bawah judul Indonesia Raya dilihat dari dekat, di alinea ketiga terbaca, “Baiklah kita pastikan lebih dulu bahwa lagu Indonesia Raya, seperti kebanyakan gubahan-gubahan komponis kita sampai sekarang, juga mempunyai retaknya, dan tidak sunyi dari kekurangan-kekurangan.” Dengan mengutip acuan Cornel Simandjuntak di majalah Arena, dikatakan, “tekanan kata dan tekanan musik yang bertentangan dalam perkataan berseru, dari kaliman ‘Marilah kita berseru'”.
Di bagian lain, komentar mereka, “Untuk memahami Indonesia Raya kita tak begitu memerlukan keistimewaan-keistimewaan dari komponisnya, cukup bila kita mengerti benar keadaan bangsa kita mengenai lahir dan batin sekitar lahirnya lagu itu.” Dan tambah mereka di alinea akhir halaman 31 ke 32, “Supratman sebagai seorang pecinta tanah air-nasionalis lebih besar dari seorang penyair-komponis. Janganlah ada yang menyesal bila nama Supratman sebagai penyair tidak terlukis dalam sejarah kesusasteraan Indonesia, dan jangan pula ada yang menyesal bila nama Supratman sebagai komponis tidak akan tertulis dalam sejarah musik Indonesia kelak.”
Oleh banyaknya kritik, maka pada 1953, dalam ulang tahun seperempat abad Sumpah Pemuda, disampaikan lagi kepada Bung Karno niat mengubah, baik nada, irama, serta syair, agar betul bebas dari bayang-bayang Lekka Lekka. Tetapi, seperti kata Koesbini kepada wartawan Top (No 29, Th IV), halnya dianggap jamak. Malah Bung Karno menghardik Koesbini di dalam rapat, “Hai, kamu seniman goblok. Kamu tidak punya kesadaran politik. Apa yang sudah diterima secara politik, tidak usah diperkarakan secara estetik.”
Pada 1953, seperti termuat di suratkabar Harian Umum, 28 Oktober di bawah artikel Atjara Seperempat Abad Indonesia Raya, ditemukan imbauan untuk menerima kata-kata dalam syair “Marilah kita berjanji, Indonesia abadi” sebagai sumpah sakti, konsensus Nasional. Semua imbauan atau masukan, diterima pemerintah sebagai bahan untuk dibuatkannya suatu peraturan resmi.
Tepat setahun sebelum Bung Karno mengeluarkan dekrit pembubaran konstituante dan kembali ke UUD 45, lahirlah peraturan baru tentang lagu ini, yang ditetapkan di Jakarta pada 26 Juni 1958 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda, serta diundangkan pada 10 Juli 1958 oleh Menteri Kehakiman G.A. Maengkom, sebagai Peraturan Pemerintah No 44.
Dalam PP No 44 itu, disebutkan pada uraian Menimbang (b): “Bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan untuk menetapkan nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan dari lagu itu serta cara penggunaannya.” Kemudian setelah itu, dikeluarkan pula penjelasan mengenai peraturan ini lewat Lembaran Negara No 72, Th 1958, yang dalam Penjelasan Umum-nya, tertera: “Tentang lagu kebangsaan, UUD Sementara RI dalam pasal 3 ayat 2 hanya memuat kalimat ‘Lagu Kebangsaan ialah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya’.
Penunjukan yang sangat singkat ini terjadi karena dianggap telah diketahui oleh umum, bahwa lagu Indonesia Raya adalah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman yang untuk pertama kalinya dinyanyikan di muka umum di Jakarta pada 28 Oktober 1928 saat diadakan Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Untuk mencapai keseragaman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah bagaimana nada-nada, irama, iringan, kata-kata, dan gubahan lagu itu,” dan seterusnya.
***
SETENGAH orang percaya, Indonesia raya dalam bentuk rekaman dibuat oleh Tio Tek Hong setahun setelah Sumpah Pemuda. Demikian juga dikatakan Oerip Kasansengari dalam memoar tadi (halaman 72), serta Sutrisno Kutojo & Mardanas Safwan dalam buku R.W. Supratman (Mutiara, Jakarta, 1979, hl. 66). Buku yang terakhir ini salah menulis Tio Tek Hong menjadi Trio Tek Hoang. Namun, majalah Star Weekly pada 1957, yang dikutip majalah Musika (No. 12, Th. I) dengan komentar khusus, mengatakan INdonesia Raya dengan suara Supratman direkam oleh Yo Kim Tjan. Masternya diserahkan sendiri oleh Yo Kim Tjan pada 1957 kepada Djawatan Kebudayaan, untuk dokumentasi, tetapi setahun kemudian diberitakan raib.
Sementara itu, Lekka lekka, pada Plat 78 Fono 2132, Euro, dalam wawancara wartawan Sinar Indonesia pada 14 Agustus 1963 dengan Salamoni, dirigen orkes harmoni kepolisian Semarang, yang memilikinya, diakui delapan bar sama dengan Indonesia Raya. Selain itu, ada juga rekaman di bawah Ultraphon, Nederland, Matrijs No. 252776, berjudul Lagoe Indonesia Rajah dengan catatan ‘marsch zonder njanjian — marsch dengen njanji’.
Setelah menjadi lagu kebangsaan, banyak kalangan masih menganggap lagu ini Barat. Tentu saja begitu, mengingat notasi yang dipakai memang Barat. Terakhir pada 1975, dalam wawancara dengan wartawan majalah Top (No.29, Th. IV), Brigjen Polisi A.J. Sudjasmin, dalam kedudukannya selaku direktur Akademi Musik Indonesia, Yogya, berkata, “Indonesia Raya belum mewakili keindonesiaan Indonesia. Tematik keindonesiaannya belum terasa.”
***
DI luar itu, lagu ini pernah heboh, sehubungan dengan kasus hak cipta, berupa penghargaan pemerintah kepada Salamah yang mengaku janda Supratman. Muasalnya terjadi tatkala Bung Karno ke Sidoarjo pada 1951. Residen Surabaya, Pamoedji, menegur Direktur Kabinet Presiden, A.K. Pringgodigdo, untuk memberikan hadiah bagi ahliwaris penciptanya yang sah. Oleh hal itu Bung Karno menyuruh mencari, siapa sebetulnya ahli waris yang sah tersebut.
Soalnya, pada 1950, muncul nama Salamah dari Kampung Kesaran, Tasikagung, Rembang yang mengaku istri Supratman. Dan terlanjur Kementerian Sosial RI, Kepala Djawatan Penjelenggaraan Sosial, Jusuradi Danudiningrat, dengan surat tertanggal Yogyakarta, 22 Djuni 1950, No. 570/Dj/II/b, mengimbau kepada Kepala Kantor Sosial Karesidenan Rembang di Pati, untuk memperhatikan nasib Salamah, antaranya memberikan uang 50-100 gulden per bulan. Tetapi dalam surat balasan Kantor Sosial daerah Pati, 5 Agustus 1950, No. 1948/Sos/III/6/50, tertanda Soekandi Handojosoesanto, hanya sanggup memberi f 15 karena alasan Salamah sudah bekerja sebagai tukang masak Rumah Kesehatan dengan gaji per bulan f 45.
Tokoh Salamah ini kemudian diragukan. Lewat RRI pada 2 Juli 1951, diberitakan, bahwa Pemerintah Pusat akan mengutus orang ke Jawa Timur, untuk menyelidik keluarga Supratman, siapa sebetulnya istri sahnya. Oleh hal itu menyebabkan Bupati Rembang, R. Soekardji Mangoenkoesoemo merasa mustahak mengirim surat, 16 Juli 1951, No.BSK/7699/II/b, kepada Kabinet RI di Jakarta, yang menguraikan lebih terinci tentang Salamah, antara lain Salamah kawin dengan Suptratman sekitar setahun sebelum Bung Karno diinternir, dan hidup bersamanya selama 17 tahun.
Baca juga: Mengenang Ignas Kleden #6: Sampah yang Berputar di Luar Rahasia
Keterangan bupati Rembang itu malah membuat keluarga Supratman curiga. Sebab jika Salamah mengaku hidup 17 tahun dengan Supratman, maka kawinnya tentu pada 1921 kala Supratman masih di Makassar, sementara Bung Karno diinternir pada 1926. Oleh kecurigaan itu, pihak keluarga Supratman melalui Roekijem Soepratijah, pada 25 Juni 1961 menulis surat kepada Menteri PD&K, Prijono, untuk meninjau kembali Bintang Mahaputra Anumerta III yang kepalang diterima Salamah. Surat itu dilampirkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1569/58/SP, yang menyebut nama-nama Roekijem, Roekinem, Nga- dini, dan Gijem, sebagai ahli waris sah. Akhirnya, karena Salamah tidak punya surat kawin, maka atas perintah Menteri Kesejahteraan Sosial, berdasarkan surat Wakil Menteri Pertama, 26 Oktober 1961, No. 25892, dan surat Menteri Kehakiman, 19 Oktober 1961, No. 484/Sek/A/31, maka Bintang Mahaputra Anumerta III dan piagamnya harus dikembalikan olehnya.
Kesimpulan sementara, Supratman tidak pernah kawin. Anehnya, dalam buku Sutrisno Kutojo & Mardanas Safwan tadi, disebutkan, ia pernah kawin dengan Mujenah, putri seorang pegawai Balai Kota di Jakarta. Dari mana sumber ini, belum jelas. Dikatakan, bahwa perkawinannya dengan Mujenah berlangsung sederhana pada 1926, dan dihadiri oleh kerabat dekat.
Ada pula sumber yang mengatakan ia menganut Ahmadiyah. Salah satu media yang menulisnya begitu adalah Utusan Indonesia, pada 28 Oktober 1950. Tetapi, selama itu berkembang juga anggapan bahwa ia kristen. Pertanyaan tentang agamanya, diajukan oleh K.H. Abdul Madjid, yang bertugas memberi doa di makam Supratman, Tambak Segaran Wetan, Kenjeran, Surabaya, pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1963. Tetapi Oerip Kasansengari, sebagai keluarganya, menyakinkan bahwa Supratman ini Islam, dan ketika ia wafat di rumah Jl. Mangga 21, Tambaksari, juga didoakan secara Islam sampai ke makamnya yang lama, Kuburan Umum Kapas.
Saya yakin masih banyak data dan sumber yang belum terkuak, yang olehnya perlu kita cari tentang diri dan karya Supratman. Dengan makin banyaknya data dan sumber, tentu akan makin memuaskan bagi kita untuk mengacu muzakarah yang selama ini mengabur. Yang disesalkan dari Solapung, adalah ia terlalu tergesa-gesa membuat suatu kesimpulan. Gayanya sama ibarat kata peribahasa: sudah mengajak berkelahi tetapi lupa belajar bersilat. Meski begitu, keberaniannya patut dihargai.
Sekedar tambahan, bukan hanya Indonesia Raya saja yang dalamnya lahir kritik, tetapi juga ciptaan Supratman yang lain, misalnya Ibu Kita Kartini. Perhatikan 8 bar yang diulang jadi 16, sama dengan Inani Keke (Minahasa) dan Bolelebo (Timor) yang keduanya bersumber dari lagu Portugis Haja Luz: E disse Deus, o, haja luz/O, haja luz, e houve luz; yakni kata-kata dari buku pertama Perjanjian Lama pasal 1 ayat 3. []
Remy Sylado, pengamat musik.