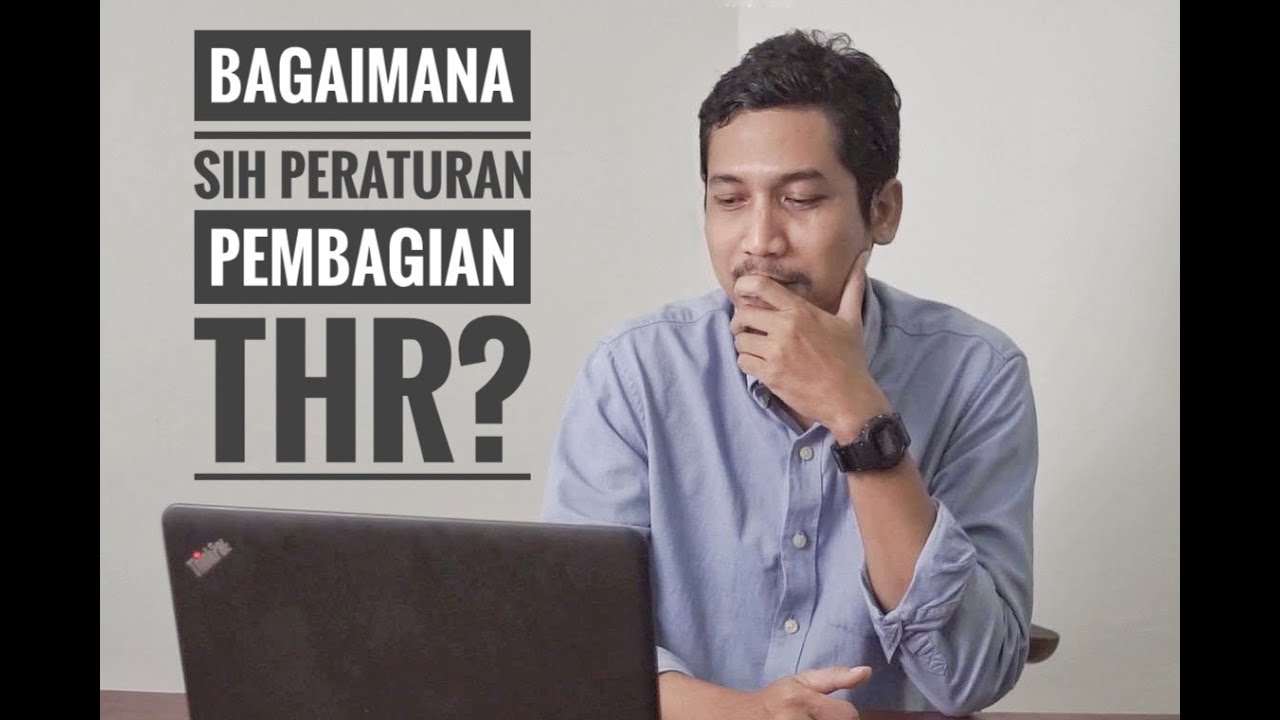Catatan redaksi: Ini merupakan kliping koran Kompas yang dilakukan oleh kerabat kerja ProPublika.id. Seri tulisan ini merupakan polemik sastra antara Ignas Kleden dan Afrizal Malna di Harian Kompas pada 1997. Tujuan utama terbitan ini adalah untuk mengenang mendiang Ignas Kleden dan pemikirannya.
Esai Afrizal Malna ini merupakan tanggapan atas tulisan Ignas Kleden berjudul Otonomi Semantik dan Intervensi Pengarang di Kompas Minggu, 10 Agustus 1997 pada halaman 21. Dalam polemik ini, sedikitnya ada enam tulisan yang bisa dilihat di tautan ini.
***
Menara Epistemologi Tanpa Telinga
Arsip Kompas Minggu, 31 Agustus 1997, Halaman 21
Oleh Afrizal Malna
MEMBACA tulisan Ignas Kleden Otonomi Semantik dan Intervensi Pengarang (Kompas, 10 Agustus 1997), saya harus kembali lagi ke pembahasan awal Ignas Kleden terhadap cerpen-cerpen pilihan Kompas (Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan). Kesempatan ini membuat saya lebih memiliki peluang untuk mengikutsertakan perhatian saya terhadap bagaimana Ignas Kleden “menilai” cerpen- cerpen lainnya. Kemudian akan lebih memperkuat apa yang pernah saya katakan dengan telah terjadinya “tabrakan wacana” dalam pembahasan Ignas Kleden.
Saya bisa mengerti apabila Ignas Kleden tidak memahami penggunaan istilah “tabrakan wacana” dalam tulisan saya (Kompas, 3 Agustus 1997). Pertama, Ignas Kleden sendiri mengakui bahwa ia menggunakan wacana sebagaimana setiap wacana merupakan sistem tertutup. Dan karena itu, kedua, Ignas Kleden menggunakannya dengan sadar. Sementara tabrakan hanya terjadi sebagai peristiwa yang tidak disadari, terjadi begitu saja.
Saya menghormati Ignas Kleden sebagai seorang epistemolog yang “patuh”. Ia memiliki kegilaan khas untuk menggunakan teori secara ketat. Baginya penggunaan teori yang fleksibel hanya akan melahirkan oportunisme epistemologis. Karena itu, memasuki tulisan Ignas Kleden, seperti memasuki sebuah menara epistemologi yang bersih, tidak memiliki telinga untuk mendengar suara-suara asing yang tidak boleh masuk ke dalamnya. Lebih lagi, saya berkesan Ignas Kleden memiliki pandangan bahwa teori adalah netral, tidak mengubah teks yang dibahas menjadi lebih baik atau menjadi buruk. Tetapi bagaimana dengan “sang pemakai” teori itu sendiri? Apakah memang mungkin berlangsung semacam mistifikasi antara teori dengan pengguna teori?
***
KALI ini saya akan menggunakan bagaimana Ignas Kleden mempraktekkan kerangka teoretiknya dalam membahas cerpen Budi Dharma (Gauhati) dan cerpen Bre Redana (Ella) dalam buku yang sama. Cerpen Budi Dharma dianggap gagal melakukan identifikasi, tekniknya ruwet. Sementara cerpen Bre Redana dinilai sebagai dunia surealistis yang masih terikat pada referensinya yang deskriptif, terpelanting dalam dunia realis yang ganjil. Metafor-metafornya tidak mendukung.
Kesimpulan itu telah membuat Ignas Kleden keluar dari menara epistemologinya sendiri, dan memperlihatkan diri dari seorang “pembahas” menjadi seorang “penilai”. Sosok teoretik Ignas Kleden yang obyektif, tiba-tiba memperlihatkan subyektifitasnya. Sementara itu Ignas Kleden masih percaya bahwa ia masih berada dalam sistem tertutup dari wacana yang telah digunakannya.
Kenapa Ignas Kleden keluar dari kerangka teoretiknya sendiri? Karena memang terdapat “guncangan identifikasi” di dalam kedua cerpen tersebut, yang mengacaukan sistem tertutup dari wacana yang digunakan Ignas. Ignas Kleden mungkin akan tetap bertahan dalam sistem tertutup ini, apabila ia justru melanjutkan pembahasannya ke arah: politik pemaknaan seperti apa yang sedang berlangsung dalam kedua cerpen tersebut, sehingga melahirkan guncangan identifikasi seperti itu. Namun Ignas Kleden justru meninggalkan ambang medan pembahasan seperti ini, kemudian melarikan pembahasannya menjadi sebuah penilaian. Kenapa? Karena ia tidak mau menjadi seorang epitemolog yang oportunistik, seorang teoretikus yang tidak bersih. Tetapi apakah guncangan identifikasi tersebut?
Dalam cerpen Budi Dharma, kekacauan identifikasi dianggap terjadi oleh Ignas Kleden, karena cerpen itu tidak jelas siapa penuturnya. Posisi saya sebagai pembaca mungkin lebih longgar dibandingkan Ignas Kleden yang ketat. Tidak ada kekacauan identifikasi dalam cerpen itu. Identifikasinya sangat jelas. Cerpen itu justru terlalu terang benderang, menjelaskan berkali-kali bahwa seluruh tokoh dalam cerpen itu mengalami krisis identitas. Gauhati menganggap tidak kenal dekat dengan Kuthari. Tamu Kuthari juga tidak kenal dekat dengan Kuthari. Tapi semuanya datang dalam pesta ulang tahun Kuthari. Gauhati kadang-kadang merasa bahwa dirinya adalah juga Kuthari. Orang tua buta penggesek biola dalam ulang tahun Kuthari, juga tidak tahu siapa dirinya. Akhirnya saya juga merasa, bahwa wajah Kuthari, wajah para tamu, dan wajah saya sendiri sebetulnya sama. Pernyataan ini diucapkan oleh Gauhati. Sebuah multi indentifikasi sekaligus mono identifikasi.
Setelah peristiwa ulang tahun itu. Kemudian terdengar kabar bahwa Kuthari tertembak mati. Tidak jelas siapa penembaknya. Cerpen ini akhirnya memang memperlihatkan betapa krisis identitas telah berlangsung sedemikian rupa. Bahkan kejahatan, penembakan gelap terhadap Kuthari, juga tidak jelas siapa yang telah melakukannya.
Hal yang sama, dengan referensi yang berbeda, juga terjadi pada cerpen Bre Redana. Cerpen ini mengangkat manekin, boneka cantik yang biasa dipajang di etalase toko pakaian. Pembaca yang hidup di kota, pasti tidak asing dengan pemandangan seperti ini. Tapi kemudian manekin dalam cerpen itu diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Boneka itu dibuat hidup sebagaimana dengan kehidupan manusia umumnya. Penerobosan batas-batas referensial dalam cerpen ini terjadi beberapa kali. Seorang lelaki berubah menjadi harimau bersayap, yang bisa menerobos jarak. Termasuk boneka berbentuk setengah anjing dan setengah kucing.
Ella, manekin itu, kemudian juga digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak, diwawancarai TV. Juga ada penyebutan nama daerah seperti Jawa Timur. Ignas Kleden kemudian menilai cerpen ini sebagai dunia surealistis yang masih terikat pada referensinya yang deskriptif, terpelanting dalam dunia realis yang ganjil. Metafor-metafornya tidak mendukung.
Sekali lagi, kenapa Ignas Kleden justru keluar dari pembahasannya, kemudian melakukan penilaian terhadap cerpen tersebut? Penilaian yang dilakukan Ignas justru mengesankan seakan-akan cerpen itu memang telah selesai hanya pada tingkat tertentu dari pembahasan Ignas. Kenapa? Karena Ignas telah menggunakan konsep surealisme sebagai sebuah wacana yang telah jadi, mapan, memiliki masa depan yang jelas.
Penerobosan batas-batas referensi yang dilakukan Bre Redana dalam cerpennya itu bagi saya telah menjalankan politik pemaknaan tertentu, yang tidak adil bila dinilai lewat konsep surealisme yang telah selesai. Referensi yang bisa digunakan dalam melihat ini, bila menggunakan lingkungan referensi dunia manekin dalam cerpen itu sendiri, menurut saya cukup sederhana. Bahwa dunia manekin merupakan fenomena di mana batas-batas referensi memang telah dilanggar. (Saya masih khawatir saya telah menggunakan istilah “Referensi” ini dengan tidak tepat, sangat takut dengan Ignas yang sangat ketat).
Kami bisa tidak perduli lagi dengan batas-batas referensi di sini. Sebab pembicaraan dalam telepon itu jauh lebih menjelaskan situasi kami daripada tempat berbeda di mana kami masing-masing berada. Dan bukankah, menjelang cerpen itu berakhir, ada sebuah pernyataan: ada beberapa hal yang benar-benar merupakan kenyataan hidup yang pernah ia lalui.
Sampai dengan akhir penilaiannya terhadap cerpen di atas, Ignas Kleden masih tetap berusaha patuh berada dalam surealisme yang dibangun dalam cerpen itu. Membiarkan setiap kesempatan melepaskan diri pada batas ambang antara realitas rekaan serta dunia nyata, lalu memasuki politik pemaknaan yang dijalankan cerpen ini: bahwa cerpen tersebut sedang mendeskripsikan fenomena “manekinisasi” yang sedang berlangsung di sekitar kita, yang menurut saya jauh lebih bermakna daripada mengidentifikasinya sebagai cerpen yang surealistis.
***
TABRAKAN wacana memang telah terjadi. Hal seperti ini mungkin terjadi untuk pembahasan yang berangkat dari wacana sebagai sebuah sistem tertutup. Sampai pada tingkat tertentu, saya tidak meragukan menilai karya sastra lewat dialektika makna dan peristiwa Paul Ricoeur yang digunakan Ignas Kleden. Saya tidak meragukan teori ini walau telah digunakan oleh Ignas Kleden untuk membuktikan cerpen saya jelek. Dan mengatakan puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri sebagai pembaruan tanpa pembuktian (lihat bahasan Ajip Rosidi hubungan antara puisi-puisi Sutardji dengan Guillaume Apollinnaire, Surealisme Prancis, atau Dadaisme, 1987: 208-226).
Tabrakan wacana seperti itu justru dibenarkan sendiri oleh Paul Ricoeur yang memang mungkin terjadi. Ricoeur melihat para strukturalis yang memperlakukan bahasa sebagai sebuah sistem, tidak berarti bebas dari kecelakaan ketaksadaran diri. Ricoeur yang selalu peka terhadap aktualitas dalam pemikiran filosofis, mengingatkan kemungkinan sistem ini tidak disadari oleh si pemakai, namun menentukan dirinya pada taraf tak sadar (K. Bertens, 1985: 454). Tabrakan di sini mungkin terjadi tanpa disadari oleh pemakainya, karena ia meyakini dirinya memang telah berada dalam sebuah sistem yang tertutup di mana tabrakan tidak mungkin terjadi. Dari dalam sistem yang tertutup ini, ia kemudian melakukan pembenaran epistemologis bahwa ia telah berada dalam posisi yang obyektif lewat penggunaan wacana yang ketat. Dari posisi ini ia kemudian menurunkan penilaian-penilaian baik, buruk, usang dan baru terhadap teks sastra yang dibahasnya.
Dalam hal ini saya memang seorang oportunisme epistemologis dalam arti positif. Tidak mencari untung atau rugi sebagaimana Ignas Kleden mencurigainya. Apabila menguntungkan, teori diterima dan ditolak apabila merugikan. Saya tidak bekerja dalam kerangka seperti ini. Saya ambil bagian dalam pembicaraan ini, hanya karena Ignas Kleden telah melakukan penilaian. Sementara itu ia juga tetap bertahan melihat teks sebagai dunia yang otonom. Teori tidak mengubah teks menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tetapi penilaian Ignas Kleden justru memasuki wilayah ini.***
* Afrizal Malna, pekerja seni.