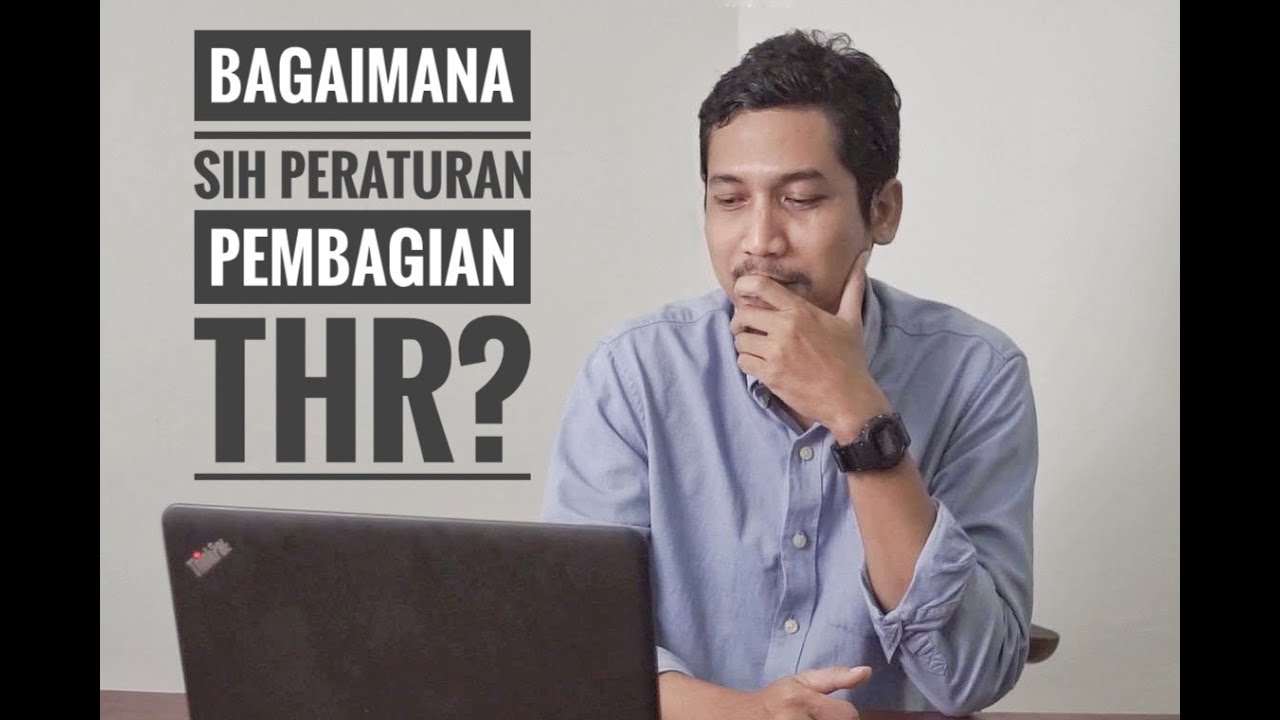Catatan redaksi: Dalam polemik sastra antara Ignas Kleden (almarhum) dan Afrizal Malna pada 1997, dua sastrawan turut memberikan komentar, yakni Budi Darma dan Nirwan Dewanto. Hal ini dibahas juga oleh Afrizal Malna dalam esai Sampah yang Berputar di Luar Rahasia (Kompas, 19 Oktober 1997).
Tulisan ini adalah hasil kliping kerabat kerja ProPublika.id, dipublikasikan ulang untuk tujuan pendidikan. Jika ada yang keberatan diterbitkannya arsip ini, kerabat kerja ProPublika.id terbuka untuk berdialog.
Polemik sastra pada 1997 ini diterbitkan ulang untuk mengenang sosiolog Ignas Kleden yang belum lama ini berpulang. Seri polemik sastra ini bisa diikuti di tautan ini: klik. Selamat membaca. Tabik!
***
Komunikasi atau Konfrontasi?
(Arsip Kompas Minggu, 14 September 1997, halaman 21)
Oleh Nirwan Dewanto
ADA penulis yang berkomunikasi dengan pembaca, ada penulis yang mau menantang pembaca. Sementara itu, karya yang konvensional belum tentu komunikatif; dan karya yang nyleneh dan eksperimental tak harus sulit diterima. Semua ini terjadi, sebab sebuah karya sastra selalu menyimpang bahkan mengkhianati maksud penulisnya.
Ketika membaca sastra, saya tak bertanya apa maksud penulis, tetapi apa makna teks. Dengan seluruh prasangka dan wawasan yang terbawa dalam diri, saya berdialog dengan teks. Dan sebuah teks yang baik, membuka diri, menyediakan pelbagai cakrawala yang bisa saya pilih untuk menguji kebenaran saya. Sedangkan teks yang buruk itu angkuh: ia mengeras menutup diri seperti sebongkah batu, atau memaksakan diri diterima seperti demagogi.
Baiklah, saya harus mengaku bahwa saya dan pembaca umumnya, dikuasai keawaman. Selera dan pikiran kami dibentuk oleh komunikasi masa, melalui iklan, kampanye, pidato, dan propaganda. Media massa mengepung kami sejak kamar pribadi sampai jalan raya. Kebudayaan yang akrab adalah kebudayaan massa. Apa yang komunikatif adalah apa yang dibiasakan, yang dibidikkan teratur ke indera kami, agar kami membeli dan memiliki barang dan gaya, pun agar kami berkata “ya” kepada tatanan yang melingkupi kami.
Keawaman, selera umum, bukanlah alamiah, melainkan sebentuk kediktatoran selera. Saya bersetuju dengan seorang pemikir Jerman: di zaman industri budaya, kepekaan estetik kita mundur, menumpul. Di tengah banjir komoditi dan kemasan, sebuah karya sastra ibarat desah yang ringkih atau justru jeritan yang subversif? Di sinilah setiap penulis tergoda: menyelesaikan diri dengan selera umum atau menantangnya?
Baik komunikasi maupun konfrontasi punya bahayanya masing-masing. Saya mencurigai karya “komunikatif” sebagai memanipulasi keawaman. Si pengarang, merasa tahu aspirasi “masyarakat luas”, berpretensi menggunakan ungkapan yang dimengerti mereka. Maka ia memperalat tokoh cerita, membebani mereka dengan (i) moralitas tertentu, merekayasa awal, klimaks, dan akhir (sekalipun dengan teknik kilas-balik). Seperti demagog, ia memperalat bahasa, sebagai kendaraan bagi gagasannya. Saya menyebut ini sebagai sikap utilitarian, bahkan fasis, dalam berbahasa. Sikap yang mematikan bahasa.
Bila bahasa cuma diperalat, cerita pun kehilangan kompleksitas. Cerita hanya mendikte, bahkan menindas pembaca. Bukan berkomunikasi, sebab komunikasi mengandaikan keaktifan pembaca. Di sini pembaca kehilangan peluang untuk ikut terlibat, membentuk dunia yang dipaparkan pengarang. Berhati-hatilah pengarang yang mau mendidik: sebab karya Anda justru bisa mengikis kecerdasan pembaca.
Saya pun mencurigai penulis “eksperimental”, yang mau menantang pembaca. Seperti pemberontak atau nabi, ia menganggap selera umum sebagai sikap jahiliyah. Ia mau melawan bahasa umum yang dianggap membodohkan sekaligus tradisi sastra yang membelenggu. Dikuasai semangat pembaruan, bahkan mungkin avantgardisme, ia seakan mabuk kata-kata. Ungkapannya seperti muntahan: menolak akal sehat, menebarkan kegilaan. Soalnya, pada titik tertentu, ia bisa sewenang-wenang: ia percaya begitu saja bahwa pemberontakannya, terornya, sebagai kebenaran yang lebih tinggi ketimbang kebenaran pembaca. Dalam nafsunya yang berlebihan mencari ungkapan dan bentuk baru, ia pun bisa bersikap fasis terhadap bahasa. Ia menganggap bahasa ia bisa dirombak secara anarkistis, seakan bahasa bukan seperangkat aturan, katakanlah sistem, yang sudah lama berlaku.
Banyak penulis yang ingin menggarap kompleksitas dalam karyanya. Namun tanpa sikap hormat terhadap bahasa, teks sastra boleh jadi hanya mengandung kegelapan, obskurantisme. Kompleksitas adalah sejumlah “jalan” yang tersedia dalam karya sastra yang bisa dipilih pembaca, agar ikut menyelesaikan dunia (cerita, tema, gagasan) yang dibentangkan di dalamnya. Kompleksitas ibarat 1001 kebenaran yang tak habis-habisnya ditafsirkan, melawan kebenaran tunggal yang dipaksakan oleh propaganda.
Sedangkan kegelapan (obskurantisme) hanya membuat kita membentur percuma, meski sekuat tenaga, ke dalam teks. Kegelapan adalah anti-komunikasi: teks sama sekali menolak berdialog dengan acuan nilai kita. Kompleksitas tumbuh dari kekuatan metafor, yakni ungkapan baru yang mengusik, mengubah, menyegarkan dan memperluas makna sehari-hari. Sedangkan kegelapan dibangun idiosinkrasi, ungkapan sepihak yang artinya dimonopoli penciptanya sendiri.
*
DIPERLUKAN disiplin naratif, kata Ignas Kleden, agar sebuah cerita make sense. Saya kira, keniscayaan ini bukan hanya berlaku bagi penulis “eksperimental”, tapi juga penulis “komunikatif”. Tanpa disiplin itu, penulis akan berlaku sewenang-wenang, dengan kata lain memupuk sikap fasis dalam berbahasa. Dalam pandangan saya, disiplin literer dimungkinkan bila penulis memandang ironis kepenulisannya, juga tradisi sastra di belakangnya. Sebab, ada sejenis heroisme yang menghidupi dunia sastra kita.
Pertama, mungkin warisan dari “sastra bertendens” (konon sastra Indonesia tumbuh bersama nasionalisme): semangat untuk mendidik, membimbing, menjelaskan, mengajar yang, dalam kadar tertentu menjelma hasrat berlebihan untuk berkomunikasi. Heroisme yang kedua, mungkin warisan dari semangat avantgardisme: semangat memberontak, memperbarui, menentang tradisi; semangat yang boleh jadi menetes ke penulis yang mau menantang (keawaman) pembaca.
Ada baiknya penulis menganggap dirinya sekadar pengrajin. Saya kira, aspek kepengrajinan (craftsmanship) inilah yang hilang dari dunia sastra Indonesia. Sebagai pengrajin, penulis benar-benar menghadapi mediumnya, yakni bahasa, sebagai organisme maupun seperangkat konvensi. Dia akan menyadari, bahasa bukanlah alat yang bisa diperintah dan dipakai begitu saja. Dia bebas memilih gagasan (tema, cerita) tapi serentak dia harus mengolahnya bersama dan di dalam -dan bukan hanya melalui bahasa. Gagasannya harus menjadi gagasan sastra, bukan gagasan yang bisa disampaikan melalui disiplin lain. Sebagai contoh, bila saya berkehendak menulis sebuah novel sejarah, saya harus menyeimbangkan gagasan sejarah di dalam gagasan naratif; bila tidak, karya saya hanya jadi bukan-historiografi pun bukan sastra, melainkan sampah. Silakan membaca historiografi beneran yang tak jarang bernilai sastra.
Sebagai konvensi, bahasa justru memungkinkan kebebasan. Menghadapi obskurantisme yang memberat dalam sebagian prosa dan puisi kita dewasa ini, saya bertanya apakah ini cerminan sikap eksperimental atau ketidakmampuan berbahasa? Mungkinkah penulisnya terlalu sadar melawan keawaman pembaca? Atau justru ia terkorupsi oleh kacaunya bahasa-politik yang menguasai massa? Yang dilawan, mestinya, bukan bahasa, tetapi perilaku buruk atau kebekuan dalam berbahasa. Puisi gelap kita, misalnya, yang pernah disangka eksperimental, segera tumbang karena mempersempit semantik dan gramatika; ia mengandung terlalu banyak idiosinkrasi yang luput dari pengalaman sosial. Sementara itu, puisi Amir Hamzah, yang sepintas-lalu terlihat antik, menyediakan kebaruan yang tak habis-habisnya.
Bahasa sudah mengandung gambaran kenyataan. Kemerdekaan penulis tak tumbuh di luar bahasa. Penulis memperluas bahasa, artinya juga memperluas gambaran kenyataan. Dalam sejarah sastra, avantgardisme adalah penolakan gambaran mapan tentang dunia. Misalnya, kaum Surealis menolak gambaran objektif yang dikorupsi moralitas borjuasi; Bertolt Brecht menampik totalitas dan gerak sejarah umum yang dipuja kaum realis, dan Armijn Pane melawan keindahan dan moralitas yang dijajakan sastra bertendens Pujangga Baru. Tentu, sekaligus mereka melawan selera umum yang, katakanlah, konservatif. Maka melawan juga berarti merombak dan menata kembali makna yang sudah terlanjur luas dipakai tapi mandul: inilah aspek teknis, disipliner, kepengrajinan, dari avantgardisme. Ya, avantgardisme bukanlah pemberontakan gratisan, muntahan eksperimentalis yang tak tahu diri.
*
SEGI disipliner inilah yang memungkinkan sastra berkembang, memperluas tradisi sastra, membentuk sejarah sastra, membuat sastra jadi fakta sosial. Dengan kata lain, tak ada karya yang, betapa pun revolusioner, tak berutang kepada tradisi dan sejarah sastra. Menyadari tradisi sastra, adalah bersikap kritis dan ironis terhadap karya sendiri: mengapa saya harus menulis bila dunia ini sudah dibanjiri karya bagus, bahkan karya besar. Bila saya mau memberontak, tidakkah saya malu, pemberontakan saya akan terjatuh pada heroisme murahan. Pemberontakan saya bukan lagi revolusi, tetapi, (seperti dinyatakan seorang penyair Meksiko), sekadar prosedur dan upacara. Penulis abad 20, di mana pun, dibuat jenuh dan bingung oleh kedahsyatan para pendahulu mereka. Tapi, tanpa tradisi sastra, penulis hanya mengulangi kekeliruan tanpa sadar. Dan bagi saya, tradisi sastra ada miripnya dengan tradisi ilmu atau tradisi sepakbola: dia tak dibatasi lingkup nasional.
Para penulis gelap kita mengira, diri mereka revolusioner, sebab mereka tak punya wawasan yang cukup perihal tradisi dan sejarah sastra. Tanpa ironi, mereka mau menggempur kemapanan sastra (sastra nasional) sekaligus melebur sastra ke dalam kehidupan. Karya mereka seperti ingin menyetarai filsafat dan jurnalisme di satu pihak serta iklan dan videoklip di pihak lain. Terbacalah ketakpuasan mereka, sastra tak cukup lagi mengucapkan kompleksitas, atau khaos, kehidupan di puncak modernitas abad 20. Dan sastra dunia mencoba memparodikan sinema, iklan, filsafat, historiografi, budaya pop, bahkan resep makanan. Tapi sastra tetaplah sastra, bukan sekadar menempel-nempelkan ungkapan pelbagai genre lain ke dalam dirinya: ia hanya berhasil bila menghisap kekuatan pelbagai genre itu dalam medium kata. Para penulis gelap mengira dapat memindahkan kompleksitas, atau khaos, begitu saja ke dalam karya mereka. Tapi, mengapa kita harus membaca karya mereka bila khaos dalam kenyataan sebenarya (jalan raya dan supermarket, misalnya) lebih menarik dan menantang?
Paruh pertama abad ini dipenuhi gerakan seni yang bernafsu melebur seni ke dalam kehidupan: ada yang anarkistis seperti Dadaisme, ada yang “teknologis” seperti Futurisme dan Konstruktivisme. Semua ini mengajarkan seni bukanlah kenyataan, tetapi representasi kenyataan. Namun sebagaimana ilmu, dia, melalui pencarian (inquiry), mengubah gambaran kenyataan. Inilah tuntutan dunia spesialis, dunia disipliner, di alam modern. Menulis adalah tindakan konseptual. Tanpa kejernihan pikiran, penulis bukan mencari, tapi tersesat. Kini kita boleh berkata, obskurantisme kita adalah (semacam) Dadaisme plus sikap takhayul minus wawasan tradisi/sejarah sastra.
Tradisi sastra juga bisa mengingatkan kaum penulis “komunikatif” sebab mereka ini bisa lebih piawai menciptakan jargon ketimbang metafor. Mereka merasa dapat menjumpai khalayak tanpa keraguan sedikit pun terhadap mutu karya sendiri. Padahal jargon memiskinkan kenyataan, mengosongkan kenyataan dari unsur subversif.
Dengan kata lain, jargon menerima begitu saja kaidah komunikasi massa tanpa menyadari muslihat dagang dan politik di baliknya. Sepintas-lalu jargon menyenangkan dan menghibur, tapi ia mengebiri cara pandang kita. Akhirnya, para penulis “komunikatif” mengira bisa mendidik khalayak, padahal karya mereka ikut melestarikan kepatuhan mayoritas. Mereka perlu kembali ke tradisi sastra: bagaimana metafor menggempur pikiran lapuk dan kebekuan berbahasa. Mereka mesti tahu, pembaca bukanlah sekadar konsumen barang (yakni karyanya): tapi juga pencipta makna yang, seperti mereka, dalam praktik berbahasa, bisa menentang penyeragaman dan pendunguan.
Tradisi sastra bukan hanya kumpulan mapan gaya sastra dalam sejarah. Dia juga mengandung persaingan antara pelbagai konsep sastra. Justru persaingan inilah yang menyelamatkan metafor dari jargon, sastra dari fasisme berbahasa, kompleksitas dari obskurantisme, dan parodi dari epigonisme. Tradisi sastra membebaskan karya dari maksud pengarang: sebab pengarang hanya “pintu” di mana bahasa yang dikandungi pengalaman dan impian sosial menyemburkan sejumlah anomali. Anomali yang sekaligus jadi umpan balik bagi sistem kebahasaan itu sendiri. Di sinilah kebebasan penulis harus dipandang ironis. Tapi ironi beginilah yang menyelamatkan dia dari nafsu memberontak maupun menggurui yang sia-sia.
*Nirwan Dewanto, Ketua Redaksi Jurnal Kebudayaan Kalam.